Program Kesehatan yang Merakyat di Zaman Silam
Usai perang, perhatian terhadap bidang kesehatan baru bisa diberikan pada 1950-an. Dari Poliklinik Keliling hingga pelayanan gratis BKIA.

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan sejak Januari lalu. Kini, muncul program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto lainnya berupa Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang dijalankan sejak 10 Februari 2025, terlepas anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tahun ini turut kena pangkas sebagai dampak efisiensi hingga Rp19,6 triliun.
Program CKG digelar dengan tiga bentuk pelaksanaan: CKG Ulang Tahun, CKG Sekolah, dan CKG Khusus Ibu Hamil dan Balita. Untuk sementara, yang sudah dimulai adalah Program CKG Ulang Tahun, di mana penerima manfaatnya adalah masyarakat umum dengan usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas bertepatan dengan tanggal ulang tahun.
“Buat yang ulang tahunnya sudah lewat di Januari dan Februari, tidak usah khawatir karena cek kesehatannya bisa dilakukan hingga akhir April,” jelas Menkes Budi Gunadi Sadikin, dikutip laman resmi Kemenkes, 10 Februari 2025.
Program CKG dihelat di sekitar 10.200 Puskesmas se-Indonesia. Secara bertahap programnya juga akan digelar di klinik-klinik kesehatan yang bekerjasama dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan.
Program CKG, menurut Kemenkes RI, didasarkan pada himpunan data yang menyatakan bahwa ada lebih dari 600 ribu angka kematian yang disebabkan penyakit kardiovaskular sebagai akibat gaya hidup tidak sehat. Oleh karenanya, program CKG tidak hanya memberikan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma tapi juga rekomendasi dan panduan untuk menjaga pola hidup sehat.
Di masa lalu pun sejumlah program kesehatan juga menyisipkan penyuluhan, rekomendasi, dan panduan-panduan serupa. Terutama beberapa program yang dijalankan di masa awal republik ini berdiri.

Aneka Pelayanan Kesehatan Cuma-Cuma
Dengan segala keterbatasan akibat perang, beberapa menteri kesehatan lebih memfokuskan perhatian pada mendirikan sejumlah fondasi tatanan kesehatan. Salah satunya pendirian Palang Merah Indonesia (PMI) pada 17 September 1945 yang diprakarsai R. Mochtar, Bahder Djohan, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan Menteri Kesehatan Dr. Boentaran Martoatmodjo.
“PMI seringkali merupakan satu-satunya sarana untuk menembus rintangan antara Republik dan Belanda. Seluruh sejarah kesehatan di zaman perang kemerdekaan ditandai dengan kerjasama yang sangat erat dengan PMI, DKR (Djawatan Kesehatan Rakjat), dan DKT (Djawatan Kesehatan Tentara),” kata buku Sejarah Kesehatan Nasional, Volume 3, keluaran Departemen Kesehatan tahun 1978.
Namun tak hanya PMI yang punya layanan gratis untuk masyarakat di masa revolusi kemerdekaan. Hal serupa sempat dijalankan Djawatan Kesehatan Kota, Kotapraja Djakarta (DKK Djakarta, kini Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta), medio 1947. Salah satunya dengan memfungsikan Rumah Sakit Rakjat di Jatinegara untuk melayani kesehatan masyarakat secara gratis.
“DKK baru mempunyai sebuah Rumah Sakit Rakjat dan didirikan di Bidara Cina (Jatinegara) pada tahun 1947 yang mempunyai kekuatan 150 tempat (tidur, red.). Rumah Sakit yang khusus disediakan untuk orang-orang miskin dengan tiada memungut bayaran,” kata buku Kotapradja Djakarta Raya.
Pada awal 1950-an, DKK Jakarta mendirikan beberapa balai pengobatan yang jadi cikal-bakal rumahsakit umum daerah (RSUD). Hingga 1952, DKK Jakarta sudah menaungi 1 Rumah Sakit Rakyat, 26 balai pengobatan, dan 3 poliklinik khusus penyakit kelamin yang total melayani hingga lebih dari 922 ribu penduduk miskin.
Khusus penduduk ibukota di perkampungan yang jauh dari jangkauan balai pengobatan, Walikota Syamsuridjal memperkenalkan program Poliklinik Keliling. Poliklinik dijalankan menggunakan mobil yang berisi peralatan medis dan obat-obatan yang beroperasi seminggu sekali untuk mendatangi daerah-daerah yang jauh dari pusat kesehatan. Peresmian programnya dihelat pada 5 Desember 1951 dengan dihadiri Presiden Sukarno.
“Pada 5 Desember 1951 dibukalah Poliklinik Keliling yang pertama di Jakarta dan yang pertama pula di seluruh Indonesia dan tercatatlah usaha yang dijalankannya rata-rata antara 100 dan 200 pasien setiap hari dapat diobati dan daerah yang dikunjunginya terutama ditujukan ke daerah-daerah perbatasan yang jauh dari tempat-tempat Balai Pengobatan yang telah ada,” lanjut buku tersebut.

Program tersebut kemudian diikuti beberapa pemerintah daerah lain. Salah satunya Pemerintah Kotapraja Makassar, medio April 1963. Program “jemput bola” guna melayani kesehatan rakyat di kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang jauh dari pusat kesehatan dan tenaga medis.
“Dengan sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh pihak Dinas Kesehatan Dati I Sulsera sampai berdirinya Poliklinik Keliling itu, pejabat Wali Kota Makassar Kapten M Dg Patompo menyampaikan terima kasihnya dalam sambutannya. Dikatakan bahwa gagasan ini timbul sejak pemerintah kota dapat laporan banyak penduduk terserang penyakit. Penduduk yang diserang penyakit ialah mereka yang tidak mampu,” tulis majalah bulanan Mimbar Penerangan edisi No. 2, 1963.
Di tahun yang sama ketika DKK Jakarta mulai menjalankan program Poliklinik Keliling, Menteri Kesehatan Dr. Johannes Leimena menginisiasi dua program prioritas: Bandung Plan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA). Program tersebut kelak diadopsi badan kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, WHO, dan menjadi cikal-bakal puskesmas.
Menurut Vivek Neelakantan dalam Science, Public Health and Nation Building in Soekarno-Era Indonesia, Bandung Plan jadi cetak biru kebijakan kesehatan Indonesia, di mana kesehatan tidak hanya melayani masyarakat tapi juga meningkatkan ketersediaan tenaga medis sekaligus distribusi dan pemerataan tenaga-tenaga medis. Bandung Plan yang digagas Leimena dibantu koleganya, dr. Abdoel Patah, cakupannya amat komprehensif, mulai dari aspek kuratif, preventif, hingga perbaikan gizi yang tak dapat dipisahkan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
“Bandung Plan digagas di Bandung karena dianggap kota itu sudah punya sistem kesehatan yang berjalan baik sejak masa Perang Dunia II. Rencananya didasarkan pada dua prinsip: integrasi aspek kuratif dan preventif dan menyeimbangkan fasilitas-fasilitas kesehatan kota dan pedesaan,” tulis Neelakantan.
Leimena memulainya dari Rumahsakit Immanuel, tempat ia pernah praktik pada 1930-an. Kala itu salah satu tantangannya adalah meyakinkan masyarakat yang mayoritas beragama Islam untuk tetap mau berobat ke rumahsakit atau klinik-klinik dan tidak perlu takut adanya Kristenisasi.
“Pelaksanaan Plan Bandung ini dimulai bulan Juni 1951 di Kecamatan Rancaekek dan Majalaya. Pelaksanaannya meliputi koordinasi rumah-rumah sakit pemerintah dan partikelir yang berada di Bandung. Di tiap kawedanan didirikan rumah-rumah sakit pembantu di bawah pimpinan juru-juru rawat terpilih dan di bawah penilikan dokter-dokter rumah sakit pusat untuk memudahkan dan melancarkan pertolongan, juga supaya di pusat tidak kejadian tempat penuh sehingga menyebabkan terlantarnya pertolongan bagi penderita-penderita,” demikian buku Propinsi Djawa Barat memaparkan.

Pelaksanaannya juga akan disokong balai pengobatan yang akan didirikan satu buah di tiap delapan desa dan satu poliklinik pembantu di setiap empat desa. Turut serta pula beberapa pusat kesehatan swasta seperti Poliklinik Muhammadiyah dan organisasi keperawatan Persatuan Djuru Kesehatan Indonesia (PDKI).
Gebrakan Leimena lainnya adalah Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA). Rella Astiannis dan Didin Saripudin dalam artikel “Johannes Leimena dalam Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia (1946-1956)” yang dimuat dalam Jurnal Factum, Volume 7 No. 2, Oktober 2018 mengungkapkan, selain menyokong Lembaga Makanan Rakyat (LMR) yang dipimpin Dr. Poorwo Soedarmo, Leimena mengadakan program BKIA berkaca dari angka kematian ibu hamil yang mencapai 12-16 persen dan angka kematian bayi mencapai 115-300 persen. Itu artinya terdapat 12-16 kematian per 1.000 ibu hamil dan terdapat 115-300 kematian per 1.000 kelahiran bayi.
“Jumlah Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak bermanfaat bagi rakyat di pedesaan maupun di kota. Jumlahnya meningkat cepat sekali, dari 387 dalam tahun 1951 menjadi 2.300 dalam tahun 1959. Letaknya tersebar di kecamatan-kecematan. Pada permulaan salah satu faktor yang menarik pada ibu dan anak berkunjung ke Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah adanya pembagian susu, sabun, vitamin, yang diberikan secara cuma-cuma. Susu dan obat-obatan itu adalah bantuan dari UNICEF,” kata buku Sejarah Kesehatan Nasional, Volume 2.
Leimena menjalankan program BKIA mirip dengan Bandung Plan. Tidak hanya melatih para tenaga medis dan para bidan, para dukun bayi tradisional pun dilatih soal sterilitas, kebersihan, dan pertolongan pertama pada persalinan. Kelak, BKIA jadi sarana untuk program Keluarga Berencana (KB).
Untuk membuat penyuluhan kesehatan menjadi aturan yang ajeg, Leimena dengan restu Presiden Sukarno “menggolkan” Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan. Dengan begitu, istilah pendidikan kesehatan mulai diperkenalkan di tiap tingkat masyarakat hingga ke kecamatan dan pedesaan melalui Balai Pengobatan maupun BKIA. Pada awal Orde Baru, persoalan pendidikan kesehatan turut dibantu tenaga spesialis pendidikan kesehatan asing serta bantuan dana USAID (Amerika Serikat) dan WHO (PBB).
“Kekuasaan yang berganti tak mematikan gagasan yang dicetuskan Leimena dan Abdoel Patah. Pada masa awal Orde Baru tepatnya di tahun 1968, gagasan Bandung Plan dipresentasikan oleh Menteri Kesehatan, Gerrit Agustinus Siwabessy. Usulan tentang pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) diterima oleh (Presiden) Soeharto dan menjadi salah satu bagian program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) Orde Baru,” tandas Ferizal dalam Sejarah Lahirnya Puskesmas, ASN, BKN, Kementerian PANRB, KORPRI, KUA, dan Akreditasi Puskesmas.
Baca juga: Dukun Beranak Ditelan Zaman








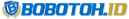










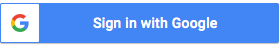

Tambahkan komentar
Belum ada komentar