
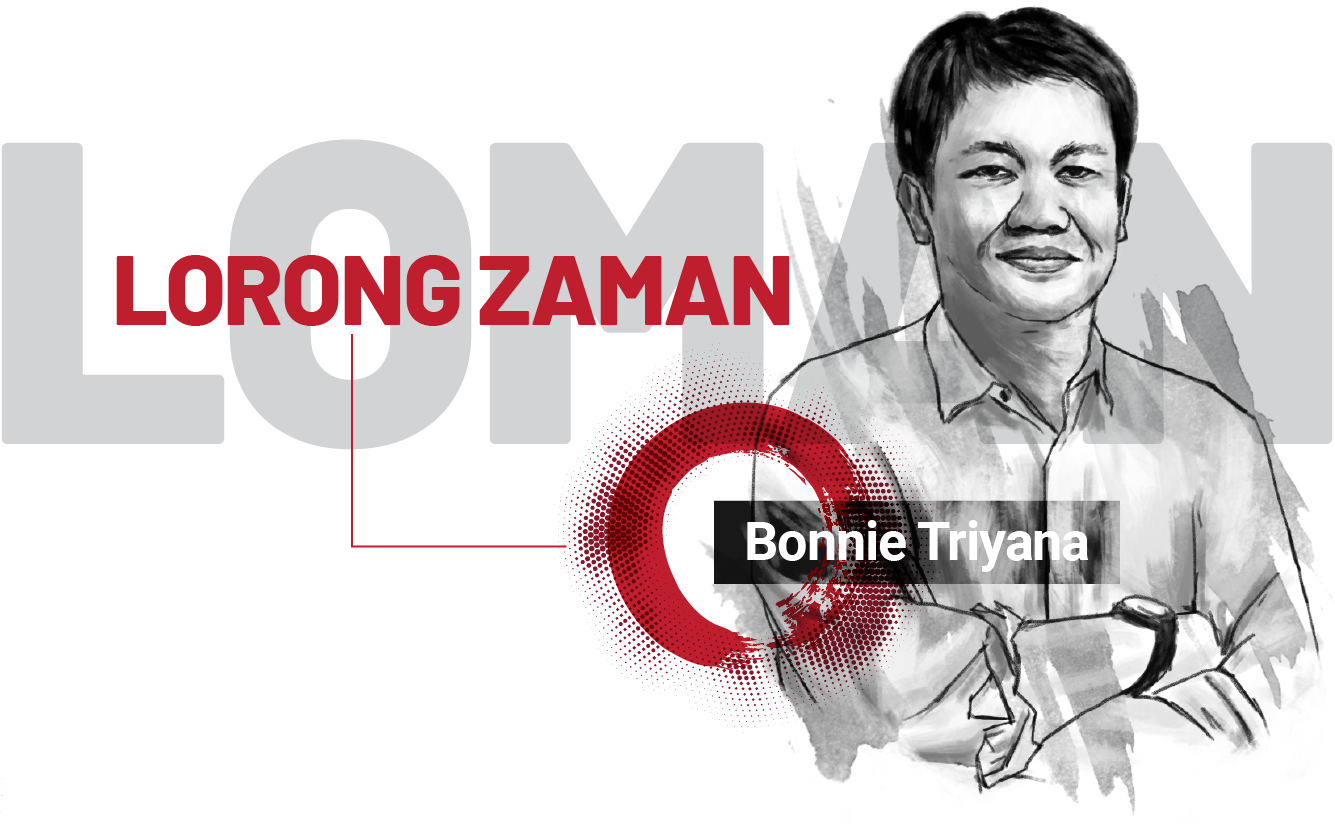
Pertandingan
JUMAT malam, 28 April lalu saya menerima kabar tentang rencana kunjungan Ganjar Pranowo, bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan. Sebagai orang yang pernah ikutan cawe-cawe dalam mendirikan Museum Multatuli, saya diminta hadir untuk menemani Ubaidilah Muchtar, kepala museum, menerima Ganjar, Sabtu, 29 April. Untuk ukuran bakal calon presiden dari partai penguasa, tak banyak orang yang ikut mengiringinya. Hanya beberapa orang terdekatnya saja yang saya duga tim inti yang memang sudah bekerja membantunya sebagai gubernur Jawa Tengah. Mungkin lain lagi kalau sudah jadi presiden, bakal lebih banyak yang mengiringinya. Itu pun kalau terpilih.
Tak ada persiapan khusus yang dilakukan staf museum. Semua berjalan biasa saja. Maklum, museum di kota tempat Multatuli pernah bertugas mulai Januari–April 1856 itu sudah terbiasa menerima tamu-tamu istimewa. Begitu pula untuk Ganjar. Kepala museum menyambutnya di pintu masuk museum, mulai menjelaskan alasan keberadaan Museum Multatuli. Ganjar sempat terkesima mendengar penjelasan Ubaidilah, terutama saat mengisahkan penugasan Eduard Douwes Dekker di Bagelen, Jawa Tengah. “Oh pernah bertugas di Bagelen juga,” kata Ganjar.
Setelah berkeliling ke seluruh galeri, Ganjar duduk di emperan panggung tempat patung Multatuli berdiri. Puluhan wartawan berkerumun, melontarkan beberapa pertanyaan sebagian besar soal alasannya mengunjungi museum. Menurut Ganjar ada tiga alasan kenapa dia berkunjung ke Rangkasbitung: pertama untuk datang ke Museum Multatuli, kedua untuk napak tilas kunjungan Bung Karno yang pernah mengunjungi kota ini pada 1943, 1951 dan 1957, ketiga utuk bertemu para ulama dan tokoh masyarakat Banten.
Menarik juga mengamati kedatangan Ganjar kali ini. Dalam dua kali Pemilu, 2014 dan 2019, perolehan suara untuk Jokowi dari daerah Banten ini tidaklah begitu gemilang. Kabarnya disebabkan isu komunis dan sentimen anti-Cina yang terus digaungkan semasa kampanye. Isu usang terus saja diputar ulang dan orang-orang menerima gosip tanpa sikap kritis. Hal yang sama juga terjadi pada Pilkada 2017, baik di Banten maupun di DKI Jakarta. Isu komunisme menggerus suara Rano Karno yang mencalonkan diri sebagai gubernur Banten, sementara isu rasialis anti-Cina dan penistaan agama membuat Ahok kalah.
Masa lalu tampak terasa tak jauh dari kehidupan masa kini. Kontestasi politik menjadikannya tetap relevan, tentu sebagai jalan untuk menjatuhkan pesaing. Kuatnya stigma komunis, sentimen rasialis, dan penggunaan isu agama atau dalam pengertian yang lebih luas: politik identitas, menguat dalam satu dekade ini. Situasi tersebut mendorong saya membuat semacam hipotesis tentang relasi ingatan kolektif atas masa lalu dengan rujukan orang dalam memberikan suaranya.
Paling tidak empat dari lima isu yang sering mengemuka dalam kontestasi politik sejak 2017 terhubung dengan memori kolektif atas sejarah. Pertama, sentimen komunisme (PKI); kedua, sentimen rasial-primordialis; ketiga, sentimen agama; keempat, sentimen sektarian; dan kelima, isu korupsi. Stigma negatif PKI, kendati tak mempan digunakan di level nasional, terbukti ampuh digunakan dalam Pilkada di Banten 2017.

Persoalannya memang bukan pada ampuh atau tidak, tapi bagaimana sentimen tersebut masih laku digunakan walaupun usaha mendekonstruksi narasi sejarah era Orde Baru yang bertumpu pada stigmatisasi komunis telah banyak dilakukan. Bahkan narasi sejarah alternatif untuk menandingi kebenaran tunggal sejarah produk rezim Soeharto pun sudah banyak dibuat, namun tak dapat begitu saja mematahkan warisan ingatan yang tertanam semenjak lama. Sentimen antikomunis menjadi pelatuk untuk meluncurkan peluru kebencian terhadap sosok tertentu untuk dibunuh karakternya.
Sementara itu baik sentimen keagamaan, rasial-primordialis maupun sektarian, menunjukkan bahwa proses pembentukan bangsa Indonesia masih jauh dari kata ideal. Idealnya, hal-hal tersebut sudah tuntas ketika para pemuda menyatakan diri berada di dalam satu ikatan kebangsaan Indonesia pada 28 Oktober 1928. Kesepakatan untuk menjadi bangsa Indonesia diperkuat pula dalam pidato Bung Karno, 1 Juni 1945, yang mengutip pengertian nasionalisme modern dari Ernest Renan: Bangsa adalah sebuah hasrat hidup bersama. Bahkan dipertegas lagi oleh Bung Karno, “Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan…”
Maka seharusnya sentimen-sentimen yang bersifat sempit dan membuyarkan kesepahaman soal bangsa tak lagi layak digunakan. Namun kenyataannya bila berurusan dengan perlombaan untuk bekuasa, segala cara digunakan untuk meraihnya. Politik memang bagai pertandingan, kadang-kadang sportif, kadang-kadang tidak juga. Ada kalanya kita tak sadar kalau sedang melestarikan tradisi berpolitik yang mengacu kepada bentuk-bentuk sentimen di atas.
Ambil contoh misalnya istilah “putra daerah” yang sering digunakan untuk menyatakan seseorang memiliki keistimewaan karena berasal dari sebuah daerah yang direken sebagai kampungnya. Entah karena sejak tujuh turunan sampai sembilan tikungan leluhurnya telah tinggal di situ atau karena numpang lahir dan hidup di sana sehingga mereka yang dapat label “putra daerah” memiliki keistimewaan dibandingkan dengan mereka yang bukan “akamsi” alias anak kampung sini.
Standar primordialistis sering kita temukan dalam berbagai perbincangan politik di tingkat lokal. Di satu sisi mengistimewakan mereka yang “putra daerah”, di sisi lainnya menutup partisipasi mereka yang mungkin lebih punya kualitas, integritas, dan potensi untuk membawa kemajuan. Padahal kesemuanya adalah warga negara Republik Indonesia.
Lain lagi ceritanya bila menyangkut soal isu rasialis. Baru-baru ini Anies Baswedan menjadi perbincangan di media sosial karena dinilai kadar keindonesiaannya kurang kuat. Terlepas dari fakta antropologis mengenai perkawinan endogami atau alasan mempertahankan nasab, ejekan bertendensi rasialis itu diwariskan dari masa lalu bangsa ini. Seperti juga yang terjadi pada Ahok yang diserang sentimen rasialis karena keturunan Cina, tampak membuatnya terjegal.
Ironisnya, mengacu pada struktur masyarakat jajahan masa kolonial di Indonesia, baik Anies maupun Ahok masuk ke dalam kategori warga Timur Asing (vreemde oosterlingen), yang derajatnya lebih tinggi ketimbang kaum bumiputra (inlanders). Tanpa sadar kita masih mempraktikan kehidupan era kolonial: terbelah secara rasial dan diskriminatif.
Yang menarik buat saya saat Ibu Mega memakaikan peci ke kepala Ganjar Pranowo sebagai simbol kebangsaan Indonesia. Pada masa pergerakan, peci menjadi penanda sekaligus pembeda mereka yang mengusung gagasan kebangsaan Indonesia. Mungkin, Ibu Mega ingin memberi pesan kepada semua untuk mengakhiri cara berpolitik warisan kolonial. Sampai mana harapan itu bisa terwujud, mari kita saksikan sama-sama pertandingan yang akan berlangsung tahun 2024 mendatang.*

