
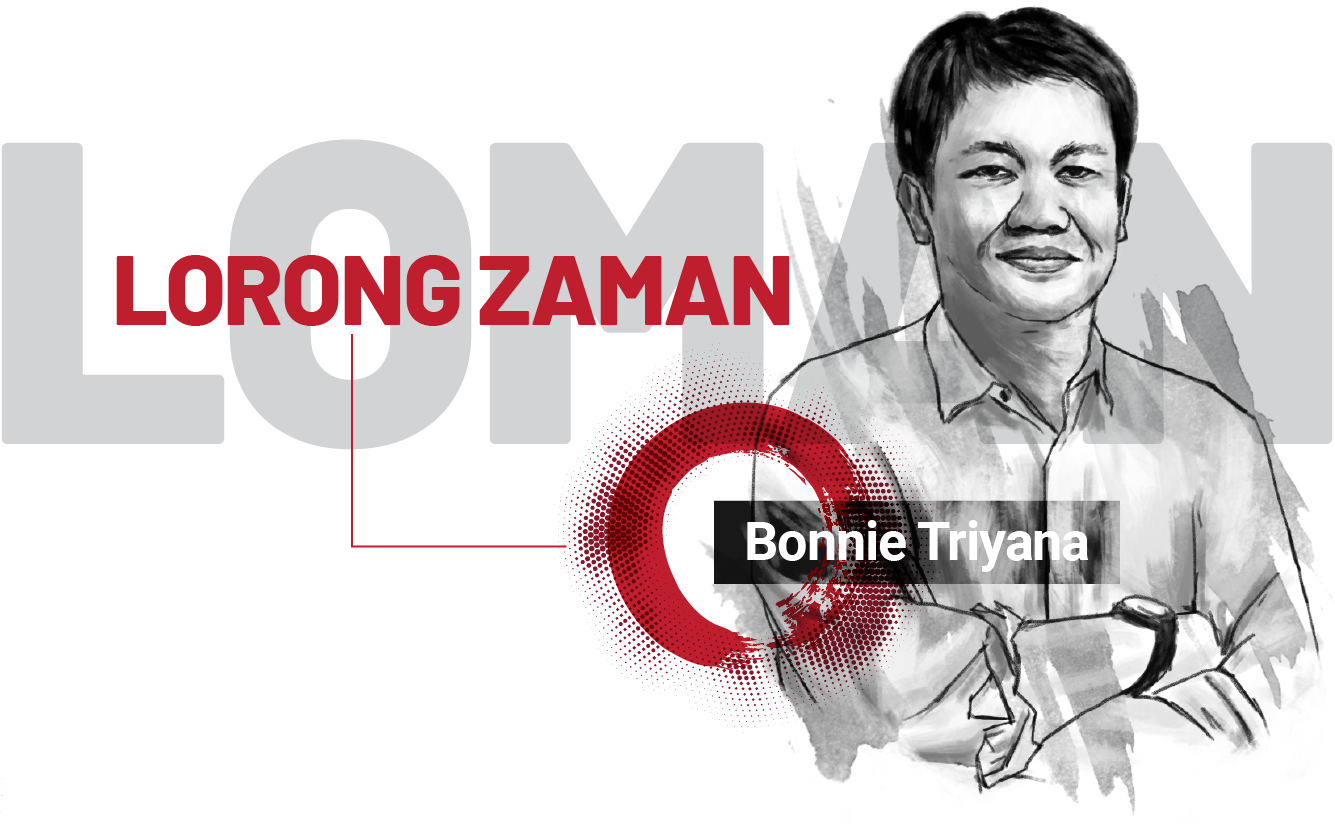
Pusaka
DALAM sebuah forum diskusi yang diselenggarakan Reinwardt Academie, Amsterdam pekan lalu, seorang peserta mengajukan kegusarannya mengapa isu repatriasi artefak budaya yang kini sedang banyak diperbincangkan terkesan didominasi oleh Barat. Kesan itu memang kuat, terlebih tren repatriasi diletupkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya ke Burkina Faso, Afrika Barat, November 2017. Dalam kesempatan itu dia mengatakan semua benda seni Afrika yang kini tersimpan di berbagai museum di Prancis harus dikembalikan ke negeri asalnya. Sejak saat itu sejumlah negara di Eropa, seperti Belanda, Jerman dan Belgia mencurahkan perhatiannya pada upaya repatriasi benda kolonial.
Pada pengujung 2020, Belanda, sebagai mantan penjajah, membentuk komite penasihat yang diketuai oleh Lilian Gonçalves-Ho Kang You, advokat terkemuka kelahiran Paramaribo, Suriname. Menanggapi pembentukan komite repatriasi di Belanda, awal 2021 yang lalu, melalui Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, Mendikbudristek Nadiem Makarim juga membentuk Tim Repatriasi Koleksi Asal Indonesia di Belanda yang diketuai oleh Duta Besar I Gusti Agung Wesaka Puja. Selain Dubes Puja yang pernah bertugas di Belanda dari 2015 sampai 2020, ada tujuh anggota ahli dan seorang sekretaris yang bertugas melakukan sejumlah perundingan dengan pihak Belanda dalam rangka pengembalian benda pusaka Indonesia yang kini tersimpan di berbagai museum di Belanda.
Di sinilah rupanya kegusaran peserta forum diskusi Reinwardt Academie bahwa isu ini didominasi Barat kurang begitu tepat. Isu repatriasi ini bukan hal baru. Jauh sebelum Emmanuel Macron angkat bicara, pada 1951 seseorang dari belahan Timur bernama Mohammad Yamin, kampiun aktivis kemerdekaan dan pengikut setia Tan Malaka, sudah lebih dulu menuntut pengembalian benda-benda bersejarah yang diambil dari Indonesia ke Belanda.
Sejak Indonesia meraih kemerdekaan 17 Agustus 1945 kemudian berlanjut ke penyerahan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar, 27 Desember 1949, benda-benda bernilai sejarah sebagai hasil dari penjajahan Belanda tidak serta merta ikut dikembalikan ke Indonesia. Yamin angkat bicara.
Dia yang saat itu duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, berniat mengajukan nota kepada pemerintah Indonesia agar menyelidiki keberadaan artefak bersejarah yang raib. Menurut catatannya, seperti termuat dalam koran berbahasa Belanda Het Nieuwsblad voor Sumatra, 3 April 1951, paling tidak ada lima fosil manusia purba dari Jawa yang lenyap dari museum Geologi di Bandung setelah Perang Dunia II selesai.
Kelima fosil tersebut adalah Homo modjokertenensis berusia 600 ribu tahun yang ditemukan di Jetis, Mojokerto, Jawa Timur; Pithecanthropus robustus dan Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah pada 1938; Pithecanthropus erectus yang ditemukan Dubois di Trinil dekat Ngawi, Jawa Timur. Fosil ini diperkirakan berusia 300 ribu tahun; Homo soloensis berusia 40 ribu tahun yang ditemukan di Ngandong, Surakarta; Homo wajakensis berusia 15 ribu tahun ditemukan di Wajak, Mojokerto, Jawa Timur.

Dari kelima fosil tersebut, hanya Pithecanthropus erectus temuan Dubois yang keberadaannya bisa ditemukan di Leiden. Menurut Yamin, fosil yang dikenal sebagai “Java Man” itu, harus dikembalikan oleh pemerintah Belanda ke Indonesia sebagai pemilik sah benda tersebut. Argumentasi Yamin tentang mengapa objek tersebut harus dikembalikan sangat kuat. Fosil tersebut adalah bukti ilmiah tentang asal-usul keberadaan manusia di Jawa, sekaligus mengukuhkan bukti bahwa Jawa adalah pulau tertua di dunia.
Tak hanya fosil manusia purba, Yamin juga menuntut Belanda mengembalikan manuskrip Nagarakretagama yang dirampas Belanda saat menyerbu istana Cakranegara di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 1894 dan arca Singosari. Kedua koleksi itu juga tersimpan di Leiden. Menurut Yamin, benda tersebut sangat berharga guna memberi petunjuk dalam penelitian mengungkap peradaban manusia masa lalu di Nusantara.
Usaha Yamin memang tak langsung terwujud. Bahkan ketika pada 1953 pengangkatannya sebagai Menteri Pengajaran Republik Indonesia pun tak seketika membawa hasil pengembalian benda-benda itu. Lama kemudian, setelah kunjungan Presiden Soeharto ke Belanda awal September 1970, hubungan Indonesia-Belanda yang sempat membeku pascakemerdekaan Indonesia, mulai mencair. Dua tahun setelah kunjungan tersebut manuskrip Nagarakretagama dikembalikan ke Indonesia. Pada 1975 kedua pemerintah menyepakati perjanjian kerja sama kebudayaan yang menjadi landasan hukum bagi pengembalian benda-benda bersejarah selanjutnya.
Tiga tahun setelah kesepakatan tersebut, arca Singosari dan benda-benda milik Pangeran Diponegoro antara lain payung kebesaran, tombak, dan pelana kuda beserta ratusan pusaka milik Puri Cakranegara dikembalikan ke Indonesia. Pengembalian berikutnya baru terjadi pada akhir 2019, ketika 1.500 koleksi yang semula dimiliki Museum Nusantara di Delft, Belanda diserahkan ke Museum Nasional Indonesia. Namun pemulangan ini di luar skema pengembalian yang ideal, di mana seharusnya setiap benda memiliki pengetahuan yang telah terlebih dulu digali melalui penelitian asal-usul (provenance research). Maklum, Museum Nusantara gulung tikar, itulah alasan pengembalian tersebut.
Kendati disertai kontroversi, keris Kiai Naga Siluman milik Pangeran Diponegoro juga akhirnya kembali pada awal Maret 2020, setelah sempat terselip entah di mana selama puluhan tahun di Belanda. Momentum pengembalian tersebut bersamaan dengan kunjungan kenegaraan Raja Belanda Willem Alexander ke Indonesia. Pemulangan keris tersebut disertai setumpuk dokumen penelitian selama puluhan tahun yang dimulai oleh Peter Pot sejak 1984, dilanjutkan oleh Johanna Leigjfeldt (2017) dan dituntaskan oleh Tom Quist pada 2019. Sehingga bisa dikatakan bukan hanya objek yang kembali, tapi juga pengetahuan mengenai keris itu turut pula bisa diketahui oleh publik.
Kasus pemulangan keris Pangeran Diponegoro itu menjadi contoh ideal bagaimana sebuah benda bersejarah dikembalikan ke negeri asalnya. Itu juga pesan penting yang bisa dipetik dari seluruh argumentasi Yamin pada tahun 1951 bahwa hal terpenting dari pengembalian benda bersejarah itu adalah produksi pengetahuan.
Produksi pengetahuan itu pula yang bisa mendorong kerja sama antarpeneliti dari kedua negara. Sehingga dalam proses kerja itu tercipta hubungan yang setara dan saling bertukar pengetahuan serta pemahaman mengenai sejarah dan kebudayaan yang melekat pada artefak yang akan dikembalikan tersebut. Karena pada akhirnya yang berharga dari benda-benda tersebut bukan saja nilai intrinsik yang terkandung di dalamnya, tapi juga nilai pengetahuan yang bisa menumbuhkan kesadaran publik mengenai arti penting sejarah dan kebudayaan sebuah bangsa. Tentu tak ketinggalan pengetahuan mengenai bagaimana kolonialisme itu sendiri, yang memungkinkan benda bernilai sejarah tinggi itu bisa diambil ke negeri penjajah lewat hubungan yang timpang dengan koloninya.*

