
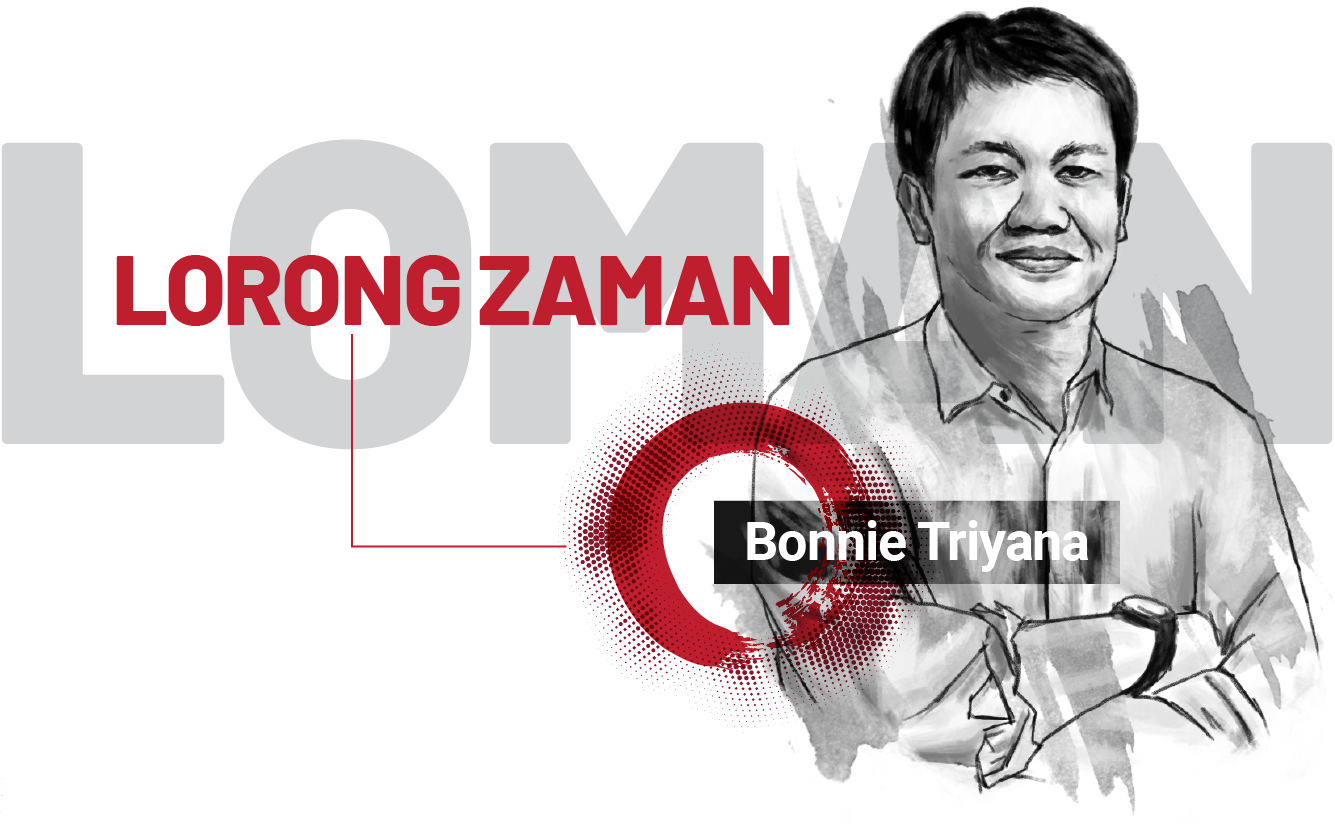
Bukan Ini, Bukan Itu
DALAM sebuah wawancara yang disiarkan salah satu stasiun televisi, Gus Dur yang saat itu belum lama dilengserkan membuat host ternganga atas jawaban yang dilontarkan presiden Indonesia keempat tersebut.
“Tadi Gus Dur mengklaim berhasil memberikan pendidikan politik kepada pendukung Gus Dur, namun mengapa banyak pendukung Gus Dur marah mengamuk dan menebangi pohon sehingga merintangi jalan raya?” kata si pembawa acara.
“Lho itu bagus daripada nebangin leher orang. Artinya saya sukses dong mendidik mereka tak melakukan kekerasan? kata Gus Dur tangkas.
Selama beberapa detik sang pembawa acara terdiam melongo, tak menyangka jawaban Gus Dur sebegitu taktisnya. Saya yang menonton wawancara itu kontan ketawa terpingkal-pingkal. Geli bercampur kagum pada kemampuan retorika Gus Dur.
Bukan Gus Dur kalau tak pernah membikin guyonan. Semasa masih jadi presiden, saya selalu menantikan kemunculannya di televisi untuk menyimak pidato ataupun komentar-komentarnya yang hampir selalu kontroversial. Bukan karena asal bunyi, tapi lebih karena ia membongkar apa yang sebelumnya orang tak pernah ketahui atau kurang bernyali untuk menyampaikannya. Sebut saja usulannya untuk mencabut TAP MPRS No. 25/1966 yang melarang penyebaran Marxisme dan Leninisme. Bisa dibayangkan kegegeran seperti apa yang tercipta akibat pernyataan Gus Dur itu.
Tak semua komentar Gus Dur bikin geger, ada pula guyonan yang memicu kita untuk berpikir. Satu hal yang menarik kita renungkan ketika Gus Dur mengatakan Indonesia adalah negara yang bukan-bukan mengacu kepada sistem kenegaraan dan praktik kehidupan berbangsa yang saling tumpang tindih serta tak sinkron satu sama lain. Sebagai negara berlandaskan Pancasila, kata Gus Dur, Indonesia bukan negara agama bukan pula negara sekuler. Jadinya negara bukan-bukan.
Lelucon itu kemudian berkembang menjadi ujaran dalam setiap diskusi mengenai situasi Indonesia, termasuk soal Indonesia negara Pancasila yang bukan kapitalis tapi juga bukan sosialis. Bukan ini dan bukan itu. Lantas apakah yang bukan-bukan itu membuat bangsa kita menjadi separuh ini dan separuh itu? Sekilas Gus Dur tampak melontarkan lelucon, namun memicu pertanyaan apakah menjadi yang bukan-bukan itu salah dan tidak memiliki akar historis?
Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa dan negara Indonesia digali oleh Sukarno semasa ia berada di dalam pengasingannya di Ende, Flores. Betapapun formulasi Pancasila adalah afirmasi atas realitas sosial dan kultural pada bangsa Indonesia, tentu tak terlepas dari cara sang penggalinya memandang dunia ini dan caranya memandang dunia erat pula dengan bagaimana dunia membentuk dirinya.
Sebagai seorang yang dilahirkan dari kultur sinkretis, Sukarno bisa luwes memandang berbagai perbedaan di hadapannya. Juga bukan soal besar baginya untuk melompat dari satu pemikiran ke pemikiran lainya, bahkan menggabungkannya guna meramu pengetahuan baru berdasarkan keperluan dan konteks bangsanya.

Pada 1926, Sukarno menulis Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai usaha sia-sia menyatukan minyak dan air. Ada konteks historis mengapa tulisan seperti demikian terbit. Sejak awal abad 20, kebangkitan kesadaran bangsa Indonesia mewujud ke dalam bertumbuhnya berbagai organisasi, baik yang bersifar etno-sentrisme, keagamaan, maupun yang berdasarkan perjuangan kelas Karl Marx. Dalam perkembangannya terjadi banyak konflik internal di kalangan bangsa Indonesia yang berisiko memecah belah dan memperlemah kekuatan melawan kolonialisme Belanda.
Melalui tulisannya, Sukarno menawarkan solusi untuk menyatukan seluruh kekuatan itu dalam satu ikatan kebangsaan Indonesia. Ia terlihat seperti mewarisi cara H.O.S. Tjokroaminoto dalam soal berpikir secara eklektik dan menggunakan metode sintesis-dialektisnya untuk memetik semua hal baik dari banyak spektrum pemikiran untuk meramunya jadi gagasan baru. Dengan metode yang sama pula Sukarno mengembangkan gagasannya tentang bentuk kebangsaan Indonesia, tak terkecuali Pancasila, di mana konsep ketuhanan sebagaimana dalam negara teokrasi berjumpa dengan demokrasi, nasionalisme, dan sosialisme secara bersamaan. Apakah ini yang membuat negeri kita jadi negara yang bukan-bukan?
Sebagai sebuah gagasan bernegara, tentu tak ada yang keliru dengan formulasi ini. Indonesia merdeka usai Perang Dunia II, saat berbagai pemikiran besar di dunia lahir, berkembang, berbenturan, dan menemukan jalannya sendiri-sendiri. Ketika bencana Perang Dunia II usai, dunia memasuki Perang Dingin yang tak lain merupakan perwujudan dari pertarungan gagasan kiri dengan kanan, kapitalisme versus komunisme. Maka dalam konteks inilah menjadi sesuatu yang bukan ini dan itu juga pilihan yang berdasar pada realitas historis.
Mungkin kritik Gus Dur dengan istilah “negara bukan-bukan” itu lebih diarahkan kepada cara kita mewujudkan konsep bernegara yang masih jauh dari ideal. Ketika praktik beragama atas nama membela Tuhan meminggirkan kemanusiaan, padahal “Tuhan tak perlu dibela,” kata Gus Dur. Juga saat negara tak hadir untuk mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan, padahal ada prinsip keadilan sosial. Suara-suara kritis dibungkam sementara penyelewengan uang rakyat terus berlangsung saat demokrasi seharusnya memberi ruang luas buat warga mengawasi jalannya pengelolaan negara. Semua itu disampaikannya pada masa Orde Baru, di saat penguasa atas nama negara, menjadi sangat dominan tanpa bisa diimbangi oleh kekuatan lain. Sementara sadar tak sadar hari ini kita masih mewarisi cara-cara yang sama dari masa lalu.
Kalau sudah begini, jangan-jangan yang paling celaka bukanlah jadi warga dari negara yang bukan-bukan, tapi lebih cenderung kepada negara yang jadi-jadian alias separuh-separuh. Separuh jadi, separuh gagal alias bantet.*










