- Remco Vermeulen
- 16 Mar 2023
- 12 menit membaca
Artikel ini merupakan artikel ketiga dari tiga tulisan mengenai kerja sama kebudayaan antara Indonesia dan Belanda. Artikel ini ditulis oleh Christopher Reinhart (Sejarawan dan Konsultan Riset Fakultas Ilmu Budaya Universitas Teknologi Nanyang), dan Remco Vermeulen (Penasihat Kerja Sama Kebudayaan dengan Indonesia di DutchCulture).
“Hubungan budaya antarnegara adalah yang paling penting. Kita perlu memahami budaya satu sama lain”, ujar Direktur Jenderal Kebudayaan Haryati Subadio pada pembukaan gedung Erasmus Huis yang baru pada tahun 1981. Sejak dibuka pada tahun 1970, pusat kebudayaan telah menandai era baru penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda, di mana kolaborasi budaya memainkan peran penting. Peranannya berkembang seiring dengan perubahan politik, pergeseran tren sosial, dan pergerakan penawaran dan permintaan. Sebagai pusat kebudayaan Belanda yang terletak di kota besar Jakarta yang terus berkembang, posisi dan pemrograman dalam kancah budaya lokal telah menjadi semakin unik.
Dari Bahasa ke Kesenian
Dalam sepuluh tahun, Erasmus Huis di Jalan Menteng Raya 25 meledak dengan pengunjung. Pada tahun 1981, Erasmus Huis memiliki sekitar 3.000 anggota, 90 % orang Indonesia dan 10 % orang Belanda. Dari 90 % ini, separuh terdiri dari orang tua yang belajar bahasa Belanda pada masa penjajahan dan separuh lainnya adalah orang muda yang tidak bisa berbahasa Belanda. Semakin lama, semakin sedikit orang Indonesia yang berbicara bahasa Belanda. NRC Handelsblad memperingatkan pada tahun 1973 bahwa “posisi bahasa Belanda terancam: dalam dua puluh tahun lagi, Indonesia hanya akan berbahasa Indonesia”. Akibatnya, program Erasmus Huis berubah dari sekadar mempromosikan bahasa Belanda menjadi menginisiasi acara-acara yang tidak lagi berfokus pada kebahasaan seperti musik, tarian, dan seni visual. Oleh karena itu, sebagian besar komunikasi dan sebagian kegiatan Erasmus Huis dilakukan dalam bahasa Indonesia. Misalnya, ada majalah KBRI Belanda, Serba-serbi Negeri Belanda, yang diterbitkan secara berkala pada periode pertengahan 1960-an hingga awal 1990-an. Pada saat yang sama, kursus bahasa Belanda diperluas. Erasmus Huis juga mengambil peran yang lebih rekreatif dan bahkan menyediakan klub catur dan bridge di malam hari.
Akses terhadap Pengetahuan
Acara yang digelar Erasmus Huis mendapat sambutan baik dari masyarakat Jakarta. Pada tanggal 23 Oktober 1971, surat kabar Kompas meliput pemutaran film yang diadakan di Erasmus Huis untuk pertama kalinya. Sejak itu, ia sering menerbitkan kolom berjudul “Event Kebudayaan” di mana kegiatan-kegiatan di Erasmus Huis diliput: antara tahun 1971 dan 1990 setidaknya ada 300 peliputan yang dilakukan tentang Erasmus Huis. Dalam beberapa tahun sejak pendiriannya, Erasmus Huis dianggap sebagai salah satu pusat budaya paling penting di Indonesia dalam hal aksesibilitas terhadap pengetahuan. Pada tahun 1976, penulis dan jurnalis Indonesia, Sides Sudyarto D.S., menegaskan di Kompas bahwa banyak anak muda mengalami kesulitan dalam menempuh pendidikan karena terbatasnya jumlah sekolah dan universitas, tingginya biaya kuliah, dan mahalnya buku pelajaran. Sudyarto menunjukkan bahwa Erasmus Huis—di samping Institut Goethe, Yayasan Idayu (sekarang tidak aktif), Sekolah Prancis untuk Kajian Timur Jauh (EFEO) dan beberapa lembaga lainnya—memberikan akses gratis kepada bacaan dan dengan demikian merupakan alternatif yang baik untuk mengakses sumber pengetahuan secara gratis.
Dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak berdirinya, Erasmus Huis dianggap sebagai salah satu pusat kebudayaan paling terkemuka di Indonesia yang berperan penting dalam aksesibilitas terhadap pengetahuan.
Pada saat yang sama, kemandirian pusat-pusat kebudayaan di Jakarta yang dibiayai pemerintah asing dipertanyakan dan diragukan: apakah penggunaan fasilitas tersebut tidak akan diam-diam mereduksi nasionalisme Indonesia? Menanggapi hal tersebut, “Paus Sastra Indonesia”, H.B. Jassin, dalam terbitan Kompas yang sama berkomentar, “Justru karena rasa nasionalisme kita, kita ingin bisa lebih memahami dunia luar. Dengan memahami dunia luar, kita akan menyadari betapa besar diri kita”. Jassin juga menepis anggapan umum bahwa Erasmus Huis mungkin memiliki pandangan bias terhadap Indonesia karena masa penjajahan Belanda dan Lembaga Kebudayaan Uni Soviet di Jakarta juga memiliki bias karena hubungannya dengan komunisme.
Lingkungan Baru dan Modern
Erasmus Huis dan gedung Kedubes Belanda di Jalan Kebon Sirih Raya 18 dengan cepat menjadi terlalu kuno dan sempit untuk pekerjaan diplomatik yang terus berkembang. Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk memindahkan fungsi diplomatik, konsuler, dan kebudayaannya ke kompleks kedutaan yang baru. Pada tahun 1976, Gubernur Ali Sadikin menawarkan sebidang tanah seluas 1 hektar di Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah lelang tender, proyek tersebut diberikan kepada PT Decoriënt Indonesia, kontraktor yang awalnya merupakan perusahaan Belanda-Indonesia: Decoriënt adalah kependekan dari Dutch Engineering Orient. Baru-baru ini, BAM International menjual Decoriënt kepada manajemennya saat ini, mengakhiri kerja sama Belanda-Indonesia yang telah terjalin lebih dari 50 tahun. Desain lingkungan yang baru dibuat oleh Sangkuriang, sebuah perusahaan Indonesia. Kompleks ini terdiri dari “departemen Konsuler, kantor konsuler empat lantai, dan Erasmus Huis dua lantai, pusat kebudayaan Belanda yang berisi perpustakaan, ruang kelas, area pameran, dan aula serbaguna berisi 300 kursi. Empat rumah untuk staf, kolam renang, gedung teknis, dan lapangan tenis ada di belakang kompleks ini”, demikianlah tertulis dalam lembar informasi Decoriënt. Kantor konsuler dan Erasmus Huis sama-sama memiliki bentuk oktagonal yang khas, dan memiliki desain yang benar-benar modern dan hampir futuristik: suatu jurang yang kentara dibandingkan akomodasi kolonial yang sebelumnya ia tempati. Pembukaan Erasmus Huis yang baru dilakukan oleh Menteri Muda Luar Negeri Belanda Durk van der Mei yang menyatakan bahwa “Belanda jarang sekali membuka pusat kebudayaan sebagus ini. Pusat di Jakarta ini hanya bisa ditandingi dengan yang ada di Paris dan Roma. Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan budaya dengan Indonesia”.
Berkat fasilitas barunya, Erasmus Huis sekarang dapat menyelenggarakan program yang lebih banyak dan besar, serta untuk audiens yang lebih luas. De Volkskrant memberi daftar acara-acara kebudayaan yang diadakan di Erasmus pada tahun 1981, yaitu pameran “Rembrandt and his contemporaries”, pertunjukan musik oleh Flairck dan ansambel Erasmus, konferensi oleh Henk van Ulsen dan kabaret oleh d’Amateurs, konferensi pendidikan untuk guru bahasa Belanda di Indonesia, pameran foto oleh Marie Bot, dan pertunjukan oleh komedian Belanda Paul van Vliet. Serba-serbi Negeri Belanda ke-44 mempromosikan festival puisi yang akan diselenggarakan, yaitu “Malam Puisi 81 Jakarta” dengan tiga belas penyair Indonesia dan lima penyair Belanda, di antaranya Remco Campert.
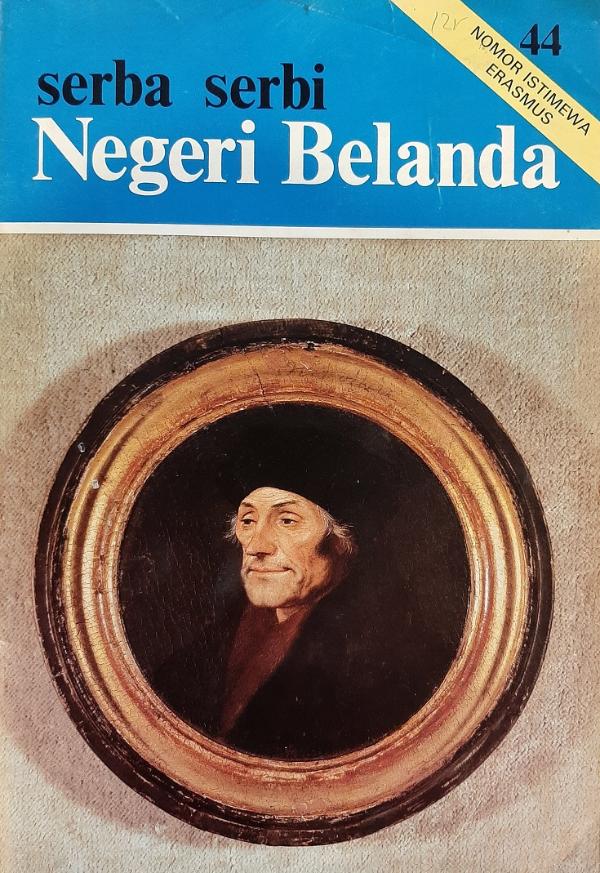
Terbuka terhadap Kritik
Festival puisi yang digelar dari 21 hingga 23 April 1981 ini kini mendarah daging dalam ingatan banyak penyair progresif yang bergulat dengan kekuasaan pada masa Orde Baru. Kompas menyebutkan bahwa dalam festival itu, penyair-penyair kritis Indonesia seperti W.S. Rendra, Sitor Situmorang (penerjemah pertama buku kritis Rob Nieuwenhuis tentang Multatuli, Mitos dari Lebak, ke dalam bahasa Indonesia), Toeti Heraty, dan masih banyak lagi hadir ke acara tersebut. Mengomentari puisi Rendra yang membahas dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan ekonomi pemerintah Indonesia—yang disambut dengan sorak-sorai para penonton pada hari kedua—surat kabar itu menulis: “dengan sajaknya, dia seperti merangkum pemikiran dan perasaan banyak orang”. Sayangnya, karena kendala bahasa, dilaporkan juga bahwa para penyair Belanda tidak mendapatkan respons yang meriah, dan “pembaca terjemahan asyik sendiri, seolah-olah tidak peduli dengan interpretasi puisi yang mereka baca”. Namun, seperti diingat Toeti Heraty dalam Media Indonesia pada 2015, “Malam Puisi 81 Jakarta” berhasil menghadirkan “banyak penyair yang sudah lama tidak kelihatan” karena iklim politik.
Meski Erasmus Huis telah menawarkan ruang aman bagi interaksi dan pertukaran budaya, tetap saja ada kritik terhadap layanannya. Pada tahun 1984, Kompas menerbitkan surat pembaca dari pengguna perpustakaan Erasmus Huis bernama Tubagus Budi Rachman. Tulisannya dimulai dengan judul menggelegar “Di Erasmus Huis, ada diskriminasi warna kulit”. Dia menulis bahwa seorang petugas di Erasmus Huis telah menegur dia dan beberapa pengguna Indonesia lainnya karena membawa tas ke perpustakaan, sedangkan peringatan sama tidak diberikan kepada “perempuan kulit putih (orang Belanda)” yang hadir. Enam hari kemudian, pengaduan tersebut langsung dijawab di surat kabar yang sama melalui pernyataan penyesalan yang ditulis oleh Direktur Erasmus Huis, Roel Verstrijden. Menurut Verstrijden, ini merupakan pengaduan pertama sejak berdirinya Erasmus Huis pada tahun 1970. Tindakan cepat yang dilakukan oleh Direktur Erasmus Huis sangat diperlukan karena pengaduan tersebut mengingatkan pada pengalaman diskriminasi yang dialami banyak orang selama masa penjajahan Belanda.
Duduk Menunggu Uang Datang
Awalnya banyak seniman Belanda yang tampil di Erasmus Huis disubsidi pemerintah Belanda. Memang, Erasmus Huis dimaksudkan untuk (kembali) menghadirkan Belanda sebagai sebuah negara lengkap dengan kebudayaannya. Terutama sekali bahasa Belanda bagi khalayak Indonesia. Catatan tahun 1989 tentang ‘Lembaga Kebudayaan Belanda di Luar Negeri’ menyatakan bahwa “promosi seperti ini adalah penjabaran dari kepentingan umum Belanda menjadi tindakan konkret di berbagai bidang, termasuk perdagangan, industri, dan pariwisata”. Subsidi kebudayaan dapat membuka jalan bagi investasi lain yang lebih menguntungkan. Namun, dampak Erasmus Huis juga harus dipahami dalam memberikan kontribusi bagi munculnya saling pengertian antara Belanda dan Indonesia, khususnya mengingat ikatan sejarah dan budaya antara kedua negara. Karena pemotongan anggaran besar-besaran oleh pemerintah Belanda selama tahun 1980-an, Erasmus Huis dan misinya tidak terlalu bergantung pada subsidi dan harus mencari sumber pendapatan alternatif. Solusi muncul lewat persewaan fasilitasnya untuk berbagai acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi eksternal, baik Indonesia maupun asing. “Kebijakan budaya Belanda tidak banyak memainkan peranan”, tulis Algemeen Dagblad pada tahun 1988, ketika mengacu pada kegiatan di Erasmus Huis. “Semakin sedikit uang pemerintah yang dimasukkan ke dalamnya, semakin bahagia pemerintah kita. Inisiatif swasta sangat disambut baik, sehingga Belanda dapat sekadar duduk menunggu uang datang”.
Perubahan Kreatif
Meskipun dana pemerintah untuk kegiatannya menurun, Erasmus Huis terus mengadaptasi programnya agar tetap relevan di antara masyarakat Jakarta. Pada tahun 1970-an, Kompas melaporkan bahwa Erasmus Huis menjadi tempat pemutaran film, pementasan wayang, dan pameran lukisan. Pada tahun 1980-an, terutama setelah pindah ke kawasan Kuningan, dilaporkan bahwa pusat kebudayaan Belanda itu mengadakan pameran foto, simposium tentang penuaan, konser Natal, seminar tentang penerjemahan dokumen hukum kolonial Belanda, dan pameran koin-koin kuno yang beredar di Indonesia. Baru-baru ini, Suni Wijogawati, pensiunan Manajer Proyek Erasmus Huis yang diwawancarai untuk artikel ini, menjelaskan sejauh mana program berubah dari waktu ke waktu. “Awalnya kami hanya fokus pada musik dan budaya klasik, tetapi sekarang kami juga merambah musik pop,” ujarnya. Teknisi Gideon Sapulete menambahkan bahwa mereka juga memberi ruang pada musik elektronik (EDM) yang sangat populer. Selain itu, di Erasmus Huis, tempat-tempat yang tidak biasa dapat diubah secara kreatif menjadi tempat acara. Rina Tjokorde, Pustakawan Erasmus Huis yang juga baru saja pensiun setelah mengabdi selama lebih dari tiga dekade, mengatakan, perpustakaan sesekali diubah menjadi tempat konser.
Hubungan yang Matang
Pada tahun 1988, surat kabar Het Parool menulis dalam sebuah artikel kecil di halaman depan tanggal 23 Februari bahwa “di Jakarta, ada gelombang nostalgia saat Belanda berkuasa di sana”. Tulisan ini bersumber dari pengamatan lebih mendalam dari New York Times yang mengungkap bahwa “kursus bahasa Belanda di Erasmus Huis terisi penuh; bangunan kolonial Belanda sedang dipugar, termasuk sebuah teater tua, yang dibangun ketika Jakarta masih menjadi Batavia. Restoran dan satu klub eksklusif yang terang-terangan membangkitkan kenangan era kolonial pun dibuka”. Artikel ini dilanjutkan dengan mengutip seorang pekerja organisasi non-pemerintah (NGO) Indonesia yang menjelaskan bahwa “orang Indonesia (…) mengenal diri mereka sendiri dan bangga dengan sejarah, budaya, dan institusi mereka” sementara “seniman dan penulis (…) mengatakan bahwa periode Belanda hanya mendisrupsi seni tradisional secara sangat terbatas. Lebih sering, orang Eropa mengambil inspirasi dari peradaban kuno yang maju di Jawa, Bali, dan pulau-pulau lain”. Baik New York Times maupun Het Parool mencantumkan kutipan dari Dirk R. Hasselman, Konselor Kedutaan Besar Belanda yang juga ditempatkan di Jakarta pada awal tahun 1970-an: “Hubungan Indonesia dengan bekas kekuatan kolonial semakin matang (…) Apa yang kita alami sekarang ini tentu tidak terbayangkan pada periode sebelumnya”. Tren ini pun terus berlanjut. Baru-baru ini, Jakarta Globe mengunjungi empat restoran kelas atas yang terletak di dalam bangunan kolonial Belanda, mengenang bahwa “Jakarta adalah salah satu kota yang memiliki arsitektur kolonial yang sangat kaya. Sementara ratusan bangunan bersejarahnya, terutama di kompleks Kota Tua, masih perlu dipugar, banyak pula yang baru saja diubah menjadi ruang publik”. Perubahan seperti itu sangat luar biasa mengingat pada awal 1960-an, hubungan bilateral antara kedua negara benar-benar terputus.

Bertepatan dengan peringatan 50 tahun Republik Indonesia pada tahun 1995, tahun yang sama di mana Ratu Beatrix, Pangeran Klaus, dan Putra Mahkota Willem-Alexander ke Indonesia untuk kunjungan kenegaraan, beberapa perusahaan swasta Belanda yang berkepentingan di Indonesia mendanai pemugaran dari rumah peristirahatan Reinier de Klerk di Jalan Gajah Madah. Bekas kediaman salah satu gubernur jenderal ini dipugar dengan cermat dan diubah menjadi kantor utama baru Arsip Nasional Indonesia. Kini, bangunan ini tersedia pula sebagai tempat pernikahan dan acara. Proyek ini dipandu oleh arsitek restorasi Indonesia dan Belanda, dan kontraktornya adalah PT Decoriënt Indonesia yang disebutkan sebelumnya. Pemugaran tersebut memenangkan Award of Excellence di Penghargaan Asia-Pasifik UNESCO untuk Pelestarian Warisan Budaya pada tahun 2001. Kedutaan Besar Belanda dan Erasmus Huis juga mendukung proyek-proyek kebudayaan yang ada dalam porsi mereka. Beberapa contohnya adalah lokakarya “Mendokumentasikan Peninggalan Arsitektur” di Jakarta dari Ikatan Arsitek Indonesia dan mitranya dari Belanda, Bond van Nederlandse Architecten (Asosiasi Arsitek Belanda), pada tahun 2003; dokumentasi Gedung A.A. Maramis (Kementerian Keuangan, dahulu Istana Daendels) tahun 2004–2005 dan 2011–2012; menjadi tuan rumah pameran Tension, 100 years architectural perspectives in Indonesia pada tahun 2007; inventarisasi benteng di seluruh Indonesia tahun 2007–2010; dan dokumentasi Museum Sejarah Jakarta pada tahun 2011.

Warisan Budaya dan Kebijakan Kebudayaan Internasional
Era reformasi, periode setelah pengunduran diri Presiden Suharto pada tahun 1998, menyaksikan peningkatan kolaborasi konservasi warisan budaya antara Belanda dan Indonesia yang dilakukan oleh arsitek restorasi swasta, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah. Sejak tahun 1997 dan seterusnya, warisan budaya tertanam dalam kebijakan budaya internasional Belanda, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Belanda dan negara-negara yang memiliki sejarah bersama, tidak hanya sebatas terkait kolonialisme. Indonesia tentu saja merupakan salah satu dari negara-negara tersebut, dan sebagai representasi budaya Belanda di Jakarta, Erasmus Huis memainkan peran kunci dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Awalnya, antara tahun 1997 dan 1999, istilah “warisan budaya Belanda di luar negeri” digunakan untuk jenis warisan khusus yang “ditinggalkan oleh Belanda, terutama pada masa Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda dan Kongsi Dagang Hindia Barat Belanda di seluruh dunia yang berupa monumen, bangunan, arsip, dan bangkai kapal”. Dengan kebijakan ini “penekanan yang kuat ditempatkan pada menemukan titik temu untuk mendukung kegiatan dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya bidang ini. Oleh karena itu, kebijakan tersebut berfokus terutama pada negara-negara di mana kehadiran Belanda memiliki makna yang lebih bertahan lama bagi penduduk setempat dan dipandang sebagai pencapaian budayanya sendiri”. Istilah “wilayah luar negeri” memiliki konotasi kolonial tertentu. Kementerian Luar Negeri dan Departemen Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan yang bertanggung jawab tampaknya juga berpikir demikian, karena mereka secara berurutan mengubah istilah dari ‘mutual cultural heritage and heritage overseas’, menjadi ‘mutual cultural heritage’, ‘mutual heritage’, ‘common cultural heritage’ antara 2000 dan 2012, dan akhirnya ‘shared cultural heritage’ dari 2013 hingga 2020. Istilah ini kembali diperbarui menjadi ‘kerja sama warisan internasional ’ untuk versi terbaru Kebijakan Kebudayaan Internasional pada tahun 2021.
Perdebatan Publik yang Panas
Debat publik di Belanda tentang sejarah kolonialnya dan dampaknya terhadap negara-negara di seluruh dunia semakin sengit dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memberi lapisan baru yang menarik pada kolaborasi warisan yang ada antara kedua negara. Di Belanda, ada perhatian khusus pada keterlibatan Belanda dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 2017, pemerintah pusat menugaskan tiga lembaga Belanda untuk melakukan program penelitian yang bertajuk “Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia, 1945–1950”, yang secara khusus “melihat sifat, penyebab, dan dampak dari tindakan kekerasan Belanda” pada periode ini. Selama kunjungan kenegaraan Raja Willem-Alexander yang didampingi Ratu Máxima dan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Bogor pada Maret 2020, sang raja berpidato tentang perang tersebut, dengan menyatakan: “Saya ingin menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas kekerasan yang berlebihan di pihak Belanda pada tahun-tahun itu. Saya melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa rasa sakit dan kesedihan keluarga yang terkena dampak terus dirasakan hingga hari ini”. Pada bulan Mei 2020, film De Oost (The East) tayang perdana di Amsterdam. Film ini mencakup perspektif seorang pemuda Belanda yang secara sukarela mendaftar untuk berperang dalam upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas koloni Indonesia, dan berbagai pilihan yang mereka buat dalam proses tersebut. Pada bulan Februari 2022, hasil dari program penelitian tersebut dipublikasikan. Karena kesimpulan utamanya menyatakan bahwa tentara Belanda secara sistematis menggunakan kekerasan ekstrem selama Perang Kemerdekaan Indonesia, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, meminta maaf kepada rakyat Indonesia.

Kerja Bersama
Dalam konteks yang dinamis ini, Erasmus Huis, serta mitra budayanya di Belanda dan Indonesia, terus mengadaptasi program dan fungsinya sebagai wadah budaya yang mengakomodasi percakapan. Dalam lebih dari 50 tahun kehadirannya di kancah budaya Jakarta, ia telah menjadi nama yang terkenal dan tempat yang populer di kalangan anak muda Indonesia. Erasmus Huis telah mendukung proyek-proyek yang menyuarakan sejarah bersama kedua negara, seperti proyek fotografi “Heritage in Transition” dan “I Love Banda” oleh Isabelle Boon, proyek fotografi Suzanne Liem “The Widows of Rawagede”, proyek fotografi multidisiplin “My story, shared history” antara seniman Indonesia dan Indo-Belanda, pameran “Segar Bugar: Kisah Konservasi di Jakarta 1920-an hingga Sekarang” dan presentasi buku terjemahan bahasa Indonesia novel Lichter dan Ik (Lebih Putih Dariku) karya Didi Michielsen. Sesekali, Erasmus Huis juga mengadakan kegiatan di Kota Tua, pusat sejarah kota Jakarta. Pada saat yang sama, pemrograman kegiatannya yang lebih tradisional seperti musik, teater, pertunjukan, serta fungsi perpustakaannya tetap konsisten. Selain menyediakan panggung untuk penyanyi, band, dan DJ Belanda di tempat mereka sendiri, atau mengatur dan mengelola tur mereka di Jawa, Bali, Sulawesi, dan Sumatra, Erasmus Huis juga mengundang seniman Belanda dan Indonesia untuk tampil dan menciptakan karya baru bersama. Nama-nama terbaru dalam daftar tersebut termasuk Junior Company of the Dutch National Ballet (yang berlatih bersama dengan Namarina Dance Company dari Jakarta), penyanyi jazz Sanne Rambags yang tampil dengan orkestra gamelan dan Wayang Gamblang Nusantara serta dalang Ki Gamblang, lokakarya oleh band rock Altın Gün yang juga tampil bersama El-Farhan, band gambus Indonesia, dan pemutaran film anak-anak Belanda dengan teks bahasa Indonesia. Kolaborasi dengan lembaga budaya Eropa lainnya di Jakarta juga terjadi dalam Europe on Screen Film Festival yang diadakan secara tahunan. Secara bertahap, Erasmus Huis memperluas kolaborasi budayanya ke disiplin budaya lain seperti film, industri kreatif, dan desain. “Building With Nature” adalah contoh baru-baru ini di mana desainer Belanda dan Indonesia bekerja sama dalam sebuah pameran tentang material berkelanjutan. Erasmus Huis juga aktif mengembangkan kerja sama dengan festival-festival di Indonesia, seperti Solo Perfoming Arts Festival dan Jakarta International Photo Festival, serta dengan akademi seni di seluruh Indonesia. Selain itu, pusat kebudayaan tersebut berupaya memanfaatkan fasilitas dan namanya untuk mengakomodasi topik lain di yang jadi perhatian Kedutaan Besar seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, dan hak LGBTQ+.
Selama beberapa dekade terakhir Erasmus Huis terus menyesuaikan programnya, memantapkan posisinya dalam kancah budaya Jakarta, menawarkan panggung bagi seniman Belanda dan Indonesia, serta memperkuat perannya sebagai pusat diplomasi budaya Kedutaan Besar Belanda di Indonesia. Dengan demikian, ia selalu tetap relevan di tengah pemerintah yang terus berganti, baik di Indonesia maupun Belanda, dan dalam dinamika hubungan yang selalu berubah antara bekas jajahan dan bekas penjajah.
Artikel ini juga ditayangkan di website DutchCulture dalam bahasa Inggris. Berikut ini adalah tautannya.













Komentar