- Randy Wirayudha
- 4 Mar 2020
- 4 menit membaca
SEJAK pengumuman kasus positif corona di Depok, Jawa Barat oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (2/3/2020), pemberitaan virus corona mendominasi pemberitaan nasional. Kasus corona bahkan memicu kepanikan masyarakat dengan memborong masker dan sembako.
Virus corona yang sebelumnya bernama “Flu Wuhan”, pernah diprediksi Dean Koontz dalam novelnya terbitan 1981, The Eyes of Darkness. Konon virus itu merupakan buah pikiran para ilmuwan China untuk kemudian dijadikan senjata biologis.
Dalam novelnya, Koontz mengisahkan virus itu bernama “Wuhan-400” lantaran dikembangkan sebagai senjata yang sempurna di laboratorium dekat kota Wuhan. Kengerian itu lalu dibocorkan seorang ilmuwan China.
“Seorang ilmuwan China melarikan diri ke Amerika membawa rekaman dalam disket tentang senjata biologis baru paling penting dan berbahaya dalam satu dekade terakhir. Mereka menyebutnya ‘Wuhan-400’ dan itu senjata yang sempurna,” kata Dombey, salah satu karakter di novel itu.
“Prediksi” Koontz itu jadi heboh di jagat maya setelah penulis Nick Hinton mengunggah salah satu bagian novel itu di akun Twitter-nya, @NickHintonn, pada 16 Februari 2020. Sebulan sebelumnya, eks perwira intelijen Israel, Dany Shoham meyakini COVID-19 alias virus corona serupa dengan garis besar kisah novel itu – berupa senjata biologis yang dikembangkan China.
“Lab-lab tertentu di institut (Wuhan Institute of Virology) mungkin terlibat, dalam hal riset dan pengembangan senjata biologis di China, setidaknya secara kolateral,” ungkapnya kepada The Washington Times, 26 Januari 2020.
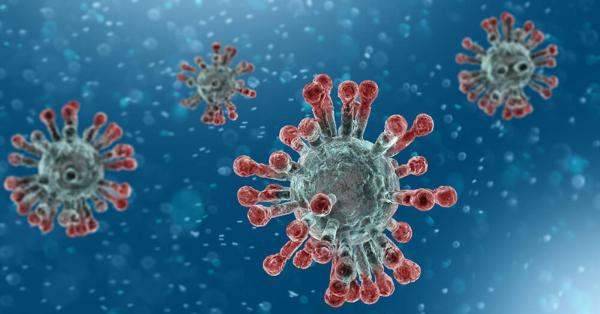
Pernyataan Shoham itu kemudian dibantah beberapa ilmuwan Amerika. Di antaranya Richard Ebright, profesor biologi-kimiawi di Universitas Rutgers. Ebright tak melihat virus corona sebagai wabah buatan manusia.
“Berdasarkan genome virusnya dan unsur-unsurnya, tidak ada indikasi apapun yang mengungkapkan bahwa virus itu adalah buatan (manusia),” sanggahnya. Terlebih jika merujuk pada karakteristik virus Wuhan-400 yang ada dalam novel dan virus corona di dunia nyata, keduanya berbeda bak langit dan bumi.
Mengutip Reuters, 28 Februari 2020, berdasarkan data WHO, virus corona berinkubasi dalam tubuh manusia dalam kurun 1-14 hari. Gejalanya berupa batuk-batuk, pilek, hingga sesak nafas. Angka kematiannya di Wuhan sebagai ground-zero berada di 2-7 persen dan di luar Wuhan 0,7 persen dari total penderita.
Namun menurut The Eyes of Darkness, thriller fiksi yang lazim punya dramatisasi ekstrem, virus Wuhan-400 disebut lebih mematikan dari virus ebola. Masa inkubasi di tubuh manusia hanya empat jam dan dipastikan angka kematian para penderitanya 100 persen. Gejala virus Wuhan-400 biasanya memangsa jaringan otak yang melumpuhkan fungsi organ tubuh.
Mula Senjata Biologis
Senjata biologis adalah senjata yang dipakai satu pihak untuk meracuni tubuh pasukan lawan menggunakan bisa serangga, racun jamur, tanaman beracun, bakteri, hingga virus agar dapat dikalahkan. Ia termasuk senjata pemusnah massal.
Mengutip Albert J. Mauroni dalam Chemical and Biological Warfare: A Reference Handbook, sepanjang sejarah, penggunaan senjata biologis terbagi pada dua periode. Pertama, periode sebelum abad ke-20, metode lazimnya adalah meracuni makanan dan air dengan racun biologis atau bakteri dari hewan dan tanaman busuk. Kedua, periode abad ke-20. Seiring perkembangan teknologi, agen-agen biologisnya sudah berupa bakteri (anthrax, brucella, tularemia), virus (cacar, virus hemoragis), serta racun (botulium, ricin, dll).
Meski penggunaan senjata biologis kemungkinan telah dilakukan jauh sebelumnya, penggunaannya dalam peperangan sudah terjadi pada Perang Troya (1260-1180 SM).
Epos Iliad dan Odyssey karya Homer pada abad ke-8 SM mendeskripsikan pasukan Yunani yang dipimpin Raja Sparta Menelaus menggunakan anak panah dan tombak yang dilumuri bisa ular. Dampaknya, musuh yang termangsa bakal mengeluarkan darah yang menghitam.
“Detail-detail dalam karya Homer itu menjadi penanda awal penggunaan racun dari ular berbisa. Dalam Odyssey, Homer menggambarkan pahlawan Yunani Odysseus juga menggunakan ekstrak tanaman beracun untuk anak panahnya. Menurut legenda kuno, sayangnya Odysseus sendiri terbunuh oleh senjata beracun –tombak yang dilumuri racun dari ikan pari, spesies yang banyak ditemukan di Mediterania,” ungkap Philip Wexler dalam History of Toxicology and Enviromental Health: Toxicology in Antiquity II.
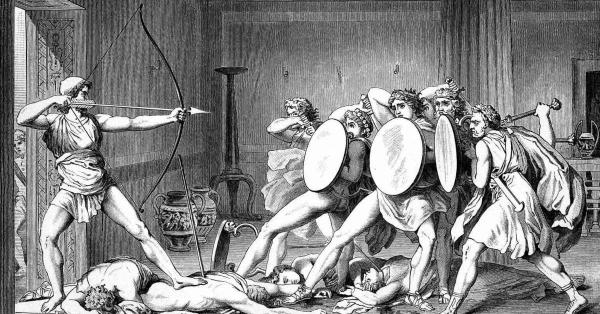
Namun, bukti tertulis itu masih berbalut mitos. Catatan pertama non-mitos baru muncul pada abad keenam SM, tepatnya pada Perang Cirraean (595-585 SM) atau pengepungan kota Cirrha oleh pasukan Yunani dari koalisi Amphictyonic League. Mereka menggunakan ekstrak racun dari tanaman helleborus untuk meracuni persediaan air kota Cirrha hingga kota itu akhirnya dihancurkan.
Pada Abad Pertengahan (Abad ke-5 hingga Abad ke-15), tren penggunaan senjata biologis dalam peperangan paling kondang adalah menyebar wabah penyakit via mayat maupun bangkai hewan yang membusuk. Itu dilakukan antara lain oleh pasukan Mongol di abad ke-13, pasukan Tartar (abad ke-14), dan pasukan Inggris pada 1340 kala mengepung kota Thun-l’Évêque di awal Perang 100 Tahun.
Penggunaan senjata biologis tertutup oleh penggunaan senjata konvensional dan senjata kimia seiring perkembangan senjata konvensional pada abad ke-20. Meski sejumlah negara tetap punya program senjata biologis, hanya ada sedikit catatan tentang penggunaan senjata biologis. Antara lain, penggunaan senjata biologis untuk misi-misi sabotase di Perang Dunia I (1914-1918).
“Di era modern, Jerman adalah negara terdepan dalam studi bakteriologi dan memulai pengunaan agen biologis. Antara 1915 dan 1917 sabotase biologis dilancarkan di Argentina, Rumania, Skandinavia, Spanyol, dan Amerika. Tujuannya mengganggu suplai hewan bagi musuh dengan menginfeksi kuda-kuda serta keledai-keledai militer, hingga hewan-hewan ternak,” tulis D. B. Rao dalam Biological Warfare.
Infeksi biasanya dilakukan dengan menularkan bakteri anthrax (bacillus anthracis) dan glanders (burkholderia mallei). Penggunaan bakteri-bakteri itu, terutama anthrax, masih tetap digunakan di masa Perang Dunia II (1939-1945).
“Di Perang Dunia II Inggris mengujicobakan efektivitas bacillus anthracis di udara terbuka dengan domba-domba mereka di Kepulauan Gruinard, serta memproduksi kue-kue yang terkontaminasi spora-spora anthrax. Mereka bermaksud menggunakannya sebagai langkah balasan jika Jerman menginvasi Inggris,” sambung Rao.

Jepang, lanjut Rao, juga diketahui memproduksi ribuan kilogram bakteri anthrax serta ratusan bakteri glanders. Di tengah berkecamuknya Perang Pasifik, Jepang mengembangkan bom-bom yang mengandung bakteri anthrax yang sudah diujicobakan dampaknya terhadap manusia. Konon, Jepang memanfaatkan sejumlah tawanan perang sebagai “kelinci percobaannya”.
Usai Perang Dunia II, pengembangan senjata biologis tetap eksis di negara-negara pemenang perang meski bergulir di bawah bayang-bayang pengembangan nuklir. Roda pengembangan teknologi senjata biologis dari waktu ke waktu makin mengerikan. Hal itu menyadarkan mereka untuk mengrem pengembangannya mengingat makin intensnya situasi Perang Dingin.
Inggris dan Uni Soviet mulai menyadarinya pada 1969. Lewat “mediasi” Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dihelatlah Konvensi Senjata Biologis pada 10 April 1972 sebagai perjanjian multilateral pertama untuk menghentikan produksi dan pelarangan penggunaan senjata biologis. Dari 183 negara yang mengikuti konvensi hanya 109 yang meneken perjanjian dan hanya 22 di antaranya yang meratifikasinya.
Faktanya, hingga milenium berganti penggunaan senjata biologis tetap tak pernah sirna. Setelah di Perang Kemerdekaan Zimbabwe (1964-1979) dengan bakteri kolera, penggunaan senjata biologis berlanjut di Perang Teluk (1990-1991), lalu di serangan terorisme (serangan anthrax) atas Washington DC, West Palm Beach, dan New York pada September-Oktober 2001.









