- Historia

- 14 Apr 2020
- 7 menit membaca
CUACA di Sirkuit Monza amat indah suatu hari medio Mei 2015. Sir Stirling Moss yang mengenakan atribut pembalap lengkap era 1950-an, hampir tak bisa berhenti tersenyum di sepanjang trek. Kakinya masih fasih menginjak pedal gas maupun kopling. Tangannya masih solid memegang setir dan persneling.
Namun tentu semuanya berbeda. Usianya sudah sepuh. Suasana sirkuit pun tak sesemarak kala ia balapan di trek yang sama pada GP Italia 1955. Meski begitu, Moss tetap bisa merasakan suasana itu kembali hidup. Tak lain lantaran mobil balap yang ia kemudikan sama persis dengan yang digunakannya enam dekade sebelumnya.
Legenda balap Inggris itu mengendarai mobil berbodi streamliner Mercedes-Benz 300SLR. Untuk menjajal beberapa lap di Monza, ia ditemani jawara F1 yang senegara dengannya, Lewis Hamilton, di kokpit mobil Mercedes W196 Monoposto atau varian awal mobil Moss di paruh pertama F1 musim 1955, sebelum berganti dengan varian streamliner.
Hamilton sesekali menyamakan kecepatan untuk mengambil posisi berdampingan sembari ngobrol kecil. Mungkin sekaligus menjaga agar Moss tak berlebihan menggeber mobilnya, mengingat usianya sudah 85 tahun.
Kenangan pada 2015 itu tak terlupakan buat Hamilton, salah satu figur F1 yang terpukul ketika mendengar Moss wafat pada Minggu (12/4/2020). Legenda balap yang sepanjang kariernya jadi raja di lintasan tanpa mahkota itu mengembuskan nafas terakhir di usia 90 tahun karena kesehatannya terus menurun.
“Hari ini kita menyampaikan selamat tinggal kepada Sir Stirling Moss, seorang legenda balapan. Tentu saya akan sangat merindukan perbincangan kami. Saya benar-benar bersyukur sempat memiliki momen istimewa bersamanya. Semoga ia beristirahat dengan tenang,” tutur Hamilton berduka via akun Twitter-nya, @LewisHamilton, 12 April 2020.
Mengubah Bully jadi Motivasi
Laman resmi F1 dalam muatan obituari Moss menjuluki sebagai “Mr. Motor Racing”. Ia legendaris sejati meski dalam rentang tujuh tahun (1955-1961) kariernya di ajang balap paling beken sedunia itu tak pernah sekalipun mencicipi gelar juara.
Moss dicap sebagai pembalap paling sportif dengan catatan turun di 66 balapan, 16 kali merebut pole position, dan 16 kali berdiri di puncak podium. Ia rival terberat sejumlah legenda lain macam Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, Jack Brabham, hingga sesama pembalap Inggris Mike Hawthorn dengan empat kali jadi runner-up (1955-1958) dan tiga kali menempati urutan tiga klasemen akhir (1959-1961).
Pria bernama lengkap Stirling Craufurd Moss itu lahir di West Kensington, London, Inggris pada 17 September 1929. Sejak kecil ia sudah akrab dengan deru mesin mobil balap. Pasalnya sang ayah, Alfred Moses, berprofesi sebagai dokter gigi sekaligus pembalap medioker. Di era 1920-an, ayahnya sering terjun di ajang-ajang amatir lokal. Sempat pula ia sekali ‘gas pol’ di ajang Indianapolis 500 pada 1924 dan finis di urutan ke-16.
Ibunya, Aileen Craufurd, semasa muda juga jadi juru balap ajang-ajang amatir balap mobil sejenis Singer Nine. Kelak adiknya yang lantas dipersunting pembalap reli Swedia Erik Carlsson, Pat Moss, juga merambah dunia balap di ajang reli.
Mengutip otobiografi yang dituliskan Moss bersama Alan Henry bertajuk All My Races, ia sudah dihadiahi ayahnya mobil Austin 7 pada usia sembilan tahun.
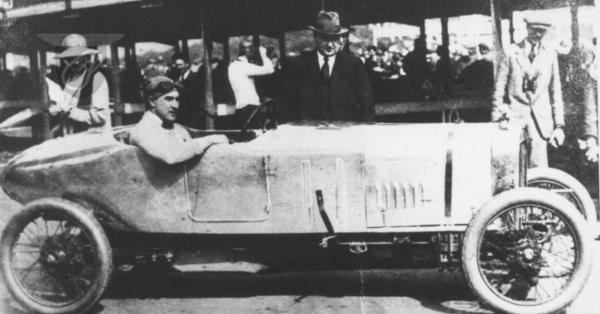
Walau hidup di keluarga dengan perekonomian yang lebih dari cukup, bocah Moss bukan tak pernah mengalami pergulatan batin. Sejak di usia sekolah dasar, ia acap jadi korbanperundungan. Utamanya perundungan bernada anti-semit karena ia punya darah Yahudi dari garis kakeknya, Abraham Moses Moss. Akibatnya, ia jadi anak yang malas ke sekolah. Beberapakali pula ia harus pindah-pindah sekolah.
“Awalnya saya selalu menyembunyikan masalah itu dari orangtua. Butuh waktu lama untuk saya bisa mengubah perundungan itu menjadi motivasi kesuksesan,” kenang Moss.
Mille Miglia dan Mahkota Formula
Mengidap nefritis atau radang ginjal membuat Moss muda tak diharuskan ikut ke medan Perang Dunia II dan wajib militer dua tahun pasca-perang. Berkahnya, pendidikannya tak terlalu terganggu oleh perang. Ia hanya harus sering ikut lari ke tempat-tempat perlindungan serangan bom tiap kali sirine meraung-raung di masa-masa Battle of Britain, 10 Juli-31 Oktober 1940.
Sejak 1948, Moss merintis karier balapnya dengan serius mengikuti beberapa ajang balap “kasta menengah” seperti Cooper 500, RAC Tourist Trophy, Alpine Rally, Goodwood Trophy, dan British Formula Three (F3).
Moss menjalani debutnya di F1 pada 27 Mei 1951 bersama tim HWM-Alta di Sirkuit Bremgarten, GP Swiss. Ia hanya mampu finis di urutan ke-14. Bukan karena kalah skill dari Fangio yang di hari itu naik ke puncak podium atau Nino Farina dan Luigi Villoresi di podium kedua dan ketiga, namun karena mobil HWM 51 bermesin Alta F2 yang dikendarai Moss kurang kompetitif.
Pada musim 1952, ia pindah ke tim ERA dengan mobil bermesin Bristol BS1 dan kemudian pindah tim Connaught, dan Cooper hingga 1953. Itu dilakoninya karena prinsip, hanya mau mengemudikan mobil bermesin dan ditopang sasis buatan Inggris.
“Lebih baik kalah terhormat dengan mobil Inggris daripada menang dengan mobil buatan asing,” cetus Moss, dikutip Paul May dalam Heroes and Saints.
Prinsip itu kemungkinan merupakan buah dari pengalaman getirnya kala merasa dikerjai Enzo Ferrari. Pada 1951, ia mulai didekati Enzo Ferrari yang menawarkan untuk mengendarai mobil Ferrari untuk ajang Formula Two (F2) di GP Bari. Tapi ketika sudah melakukan perjalanan jauh dari London ke Puglia, Moss yang ditemani ayahnya, hanya mendapati satu-satunya mobil Ferrari adalah mobil yang dikendarai pembalap Piero Taruffi.
Masalahnya tak satupun staf tim Ferrari yang bisa memberi penjelasan memuaskan. Akhirnya Moss dan ayahnya pulang dengan memendam dengki. Maka hingga 1954 ia tak pernah sekalipun mau menyentuh mobil-mobil pabrikan asing. Namun karena catatan awal kariernya (1951-1953) yang sama sekali tak menggembirakan, ditambah nasihat-nasihat para sponsor, Moss akhirnya berkenan masuk ke kokpit mobil asing, yakni Maserati 250F di tim Alfieri Maserati asal Italia.
“Moss bisa tampil di musim 1954 dengan mobil (Maserati) 250F, di mana finansialnya disponsori Shell-Mex dan BP. Moss merasakan sendiri betapa bagusnya handling mobil 250F sebagai wahana yang ideal untuk mendemonstrasikan skill-nya,” tulis Stuart Codling dalam Art of the Formula 1 Race Car.
Prestasi Moss pun mulai moncer sejak mengendarai Maserati. Di pentas F1 ia memang hanya merasakan sekali naik ke podium ketiga di GP Belgia, 20 Juni 1954. Tetapi di luar F1, tahun itu Moss mendulang beberapa gelar dengan mobil 250F, di antaranya International Gold Cup dan Goodwood Trophy.
Semusim berikutnya, ia pindah ke tim Mercedes. Di sinilah nama Moss mulai jadi langganan calon juara F1. Di musim 1955 dengan mobil Mercedes W196, Moss tiga kali naik podium, termasuk kemenangan pertamanya di GP Inggris, 16 Juli 1955 yang dihelat di Sirkuit Aintree, Liverpool. Bahkan di akhir musim, ia sukses menguntit Fangio yang juga rekan setimnya menjadi runner-up, sekaligus mengangkangi dua pembalap Ferrari, Eugenio Castellotti dan Maurice Trintignant, yang hanya mampu bercokol di urutan tiga dan empat klasemen akhir.

Namun kenangan yang tak pernah dilupakannya di tahun 1955 justru keikutsertaannya di ajang Mille Miglia. Bersama co-driver Denis Jenkinson, Moss memenanginya. Itu menjadi kali pertama Moss memenanginya sejak ikut Mille Miglia pada 1951.
Mirip Le Mans 24 Hours, Mille Miglia adalah ajang balap ketahanan mobil dan pembalap. Bedanya, Le Mans dibatasi waktu 24 jam, sementara Mille Miglia waktunya non-stop selama 10 jam dengan jarak tempuh 1.500 kilometer dengan start-nya dimulai dari Brescia dan finis di Roma.
“Menang Mille Miglia lebih sulit daripada Le Mans 24 Hours. Tingkat stres di dalam mobil lebih tinggi. Anda juga balapan di jalanan umum dengan intensitas selama 10 jam. Balapan di jalanan umum di mana Anda tak mengenal treknya sangat berbeda dan sangat menuntut teknik. Anda tidak bisa mempelajari karakter trek sepanjang 1.000 mil,” sambung Moss dalam otobiografinya.
“Belum lagi penonton yang berdesak-desakan di pinggir treknya membuat Anda tak bisa melihat ujung tepi tikungan. Tapi sepanjang karier kemenangan itulah pencapaian terbaik saya. Anda tak bisa membandingkan misalnya dengan kemenangan saya di GP Monaco 1961. Segalanya bergantung pada kepercayaan diri, baik terhadap mobil maupun kemampuan Anda,” lanjutnya lagi.
Pada musim 1958, Moss hanya kalah sebutir poin dari kompatriotnya, Mike Hawthorn, dalam perebutan juara F1. Tak pernah sepanjang kariernya gelar juara begitu dekat dengan genggamannya. Di musim itu, Moss empat kali menang dan mengumpulan 41 poin. Adapun Hawthorn cuma sekali menang tetapi punya perolehan 42 poin. Penyebabnya, Moss lebih sering gagal mendapatkan poin karena gagal finis di lima seri, sementara Hawthorn hanya dua kali.
Namun yang paling menjadi perhatian utama adalah sikap sportif Moss terhadap Hawthorn di GP Portugal yang dihelat di Sirkuit Boavista, 24 Agustus 1958. Mengutip majalah Motor Sport edisi Oktober 1958, mobil Hawthorn tergelincir di sebuah tikungan pada lap ke-48. Masalahnya saat itu kondisi tikungannya menanjak, menjadikan Hawthorn sukar menyalakan lagi mesin mobilnya. Satu-satunya cara adalah didorong ke jalanan menurun dan itu artinya Hawthorn harus berbalik arah.
Itu kemudian dipermasalahkanpengawas balapan (steward). Hawthorn dianggap menjalankan mobilnya berlawanan arah di luar trek dan itu merupakan pelanggaran. Hasilnya, Hawthorn yang finis kedua di belakang Moss, didiskualifikasi.
“Tapi pada rapat ofisial balapan di malam hari setelah balapan, Moss memberi kesaksian bahwa Hawthorn mencoba menyalakan lagi mesinnya dengan didorong di sisi dalam bantalan tepi trek, bukan di luar dan oleh karenanya tidak melanggar peraturan. Lalu pada jam 11 malam ofisial balapan memberi keputusan mengembalikan status runner-up Hawthorn,” tulis majalah itu.

Andai Moss tak berinisiatif dan bersikap sportif untuk memberi kesaksian pada ofisial balapan GP Portugal, Hawthorn takkan mendapatkan tambahan tujuh poin. Itu berarti di akhir musim sangat mungkin Moss-lah yang keluar sebagai juara dunia, bukan Hawthorn.
“Bagi saya, Mike tak semestinya didiskualifikasi. Saya merasa, keputusan steward telah salah mendiskualifikasinya. Dan saya memberi kesaksian bahwa dia masih di dalam trek, tepatnya di escape road (jalur darurat, red.) yang kemudian diterima ofisial. Nyatanya hal itu membuat saya kehilangan gelar. Walau demikian (sikap sportif) sudah berarti kemenangan buat saya,” tambah Moss.
Di pengujung musim, Moss akhirnya gagal juara. Meski pedih, tiada penyesalan dalam hatinya.
“Memang sempat ada sedikit rasa kesal karena saya merasa harusnya tahun itu saya juara. Saya merasa punya kemampuan untuk jadi juara tapi nyatanya saya tidak juara. Mike adalah teman baik saya. Tentu saya merasa mampu mengalahkan dia, tetapi harus diterima juga bahwa saya kalah satu poin darinya,” tandas Moss yang pensiun pada 1962 akibat cedera parah usai kecelakaan di ajang Glover Trophy.













Komentar