Berbagai Rupa Program Perbaikan Gizi Era Orba
Jangan sampai rakyat lapar. Kelaparan menciptakan sekumpulan orang pemarah dan menghambat pembangunan. Begitu kata Presiden Soeharto.

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto jadi ujung tombak upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi bagi masyarakat saat ini. Namun, jauh sebelum itu, pemerintah dari masa ke masa sudah memperjuangankan hal serupa. Persoalan di bidang gizi ini lantaran kebanyakan masyarakat berpikir makan sekadar untuk kenyang atau bertahan hidup. Alih-alih untuk hidup sehat, kandungan gizi yang mesti terpenuhi dalam porsi makanan acapkali diabaikan.
Slogan “4 Sehat 5 Sempurna” pernah jadi kampanye yang digaungkan pemerintah pada era 1950-an. Dalam kampanye itu, masyarakat diajak untuk memenuhi semua unsur gizi setiap kali makan, mulai dari karbohidrat, protein, mineral, vitamin, hingga minum susu sebagai penyempurnanya. Tapi, nasi masih mendominasi ketimbang sumber nutrisi lainnya. Maka pada paruh pertama 1960, Presiden Sukarno mencanangkan revolusi menu makanan. Gebrakan ini bertujuan agar masyarakat punya menu makanan bervariasi, tidak hanya berpaku pada nasi untuk pemenuhan kebutuhan gizi.
Memasyarakatkan konsep makan seimbang untuk pemenuhan gizi demi kesehatan tampaknya masih belum teratasi memasuki era Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dengan masa berkuasa paling lama menjadi rezim paling banyak menelurkan program terkait perbaikan gizi. Setelah Presiden Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat, program-program terkait pangan, gizi, dan kesehatan –yang semua berkaitan– bermunculan.
Usaha Perbaikan Gizi Keluarga
Pada masa transisi memasuki Orde Baru, upaya peningkatan gizi masyarakat terkesan mandek, bahkan dekaden. Hal ini tidak terlepas dari situasi stabilitas negara yang tengah dilanda krisis politik dan krisis ekonomi. Inflasi membubung tinggi diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok. Jangan tanya bagaimana kondisi gizi masyarakat kebanyakan, bisa cukup makan saja sudah bagus.
“Harga-harga kebutuhan hidup terus merayap naik. Inflasi meningkat tajam, bahkan hingga beberapa ratus persen. Berbagai bahan kebutuhan pokok masyarakat semakin sulit didapat,” kenang Firman Lubis dalam Jakarta 1960-an.
Indonesia sebenarnya menjadi salah satu negara penerima bantuan program peningkatan gizi masyarakat (Applied Nutrition Program/ANP) dari PBB. Namun, ketika Presiden Sukarno memutuskan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB, bantuan itupun terhenti. Setelah Indonesia masuk kembali ke dalam PBB, program bantuan yang didanai UNICEF tersebut berjalan lagi.
“Kegiatan penanganan gizi disempurnakan organisasinya dan dikenal dengan istilah Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) yang diperluas ke seluruh Indonesia,” ulas Yessy Aprihatin, dkk. dalam Intervensi Pencegahan Stunting Berbasis Lingkungan.
Kegiatan UPGK awalnya dikonsentrasikan pada 8 provinsi: Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Kegiatannya disesuaikan dengan keadaan daerah setempat. Sejak saat itu kegiatan perbaikan gizi mulai dikenal oleh masyarakat luas.
Pencanangan UPGK dibarengi dengan riset dan studi untuk mendukung program tersebut. Pada 1967, mulai diadakan pelatihan-pelatihan ilmu gizi yang pertama di Indonesia. Setahun berselang, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memprakarsai simposium tentang persoalan pangan dengan menggandeng akademisi dan ahli pangan dari lembag AS, National Academy of Sciences. Simposium ini selanjutnya menjadi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) yang diselenggarakan secara berkala setiap empat tahun sekali semenjak 1973 oleh LIPI.
Tugas-tugas UPGK meliputi 6 proyek. Mulai dari proyek pelatihan, proyek peternakan, proyek perikanan, proyek kebun sekolah, proyek kebun halaman, dan proyek kesejahteraan keluarga. Namun, dalam praktiknya publikasi program UPGK ini kurang begitu menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput.
Menurut Harian Kami, 21 April 1971, pada umumnya para pejabat dan petugas pada berbagai tingkat yang telah mendapatkan penambahan pengetahuan tentang UPGK kurang menyebarluaskannya kepada masyarakat. Pada 1971 merupakan tahun diselenggarakannya pemilu pertama di masa Orde Baru sehingga banyak terjadi pergantian pejabat di departemen negara. Selain itu, program UPGK dinilai belum menyentuh daerah tertinggal yang seyogianya lebih membutuhkan.
“Dikemukakan bahwa belum cukupnya penjelasan tentang pengertian UPGK dan seringnya penggantian pejabat di pusat, daerah, lembaga, dinas jawatan yang bersangkutan menyebabkan pelaksanaan UPGK selalu terhambat,” lansir Harian Kami.
Instruksi Presiden
Karena masih banyak kekurangan di sana-sini, program UPGK pun dievaluasi. Menurut tim penelitian Departemen Kesehatan (Depkes), konsep UPGK belum menyentuh persoalan gizi di Indonesia. UPGK terlalu menekankan pada masalah kekurangan protein, padahal masalah yang dihadapi adalah kekurangan kalori dan protein (KKP). Upaya penyuluhan juga belum tepat sasaran karena kelompok masyarakat yang KKP terutama golongan di bawah garis kemiskinan. Selain penyuluhan gizi, mereka ternyata memerlukan tambahan asupan makanan. Pada intinya penyampaian program UPGK di lapangan mengalami sejumlah hambatan.
“UPGK masih kurang mendapat dukungan lintas sektoral. Hal ini disebabkan karena bahasa yang digunakan terlalu teknis medis, sehingga kurang dipahami oleh masyarakat awam dan pembuat kebijakan. Untuk itu perlu digunakan bahasa yang mudah dimengerti,” catat Sajogyo dan tim Ditjen Pembinaan Kesehatan Depkes dalam Usaha Perbaikan Gizi Keluarga.
Pada September 1974, Presiden Soeharto menerbitkan Inpres tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat. Melalui Inpres tersebut, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi makanan rakyat, baik kualitas maupun kuantitas. Agenda ini terbilang proyek besar karena lintas sektoral yang melibatkan 10 kementerian: Kementerian Negara Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Negara Ekonomi dan Keuangan/Kepala Bapennas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Penerangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan.
Menurut Presiden Soeharto, rendahnya mutu gizi masyarakat menghambat jalannya pembangunan. Ia bisa mendatangkan bencana pada suatu bangsa. Sebut saja memerosotkan kehidupan, angka kematian tinggi pada bayi dan anak-anak, terganggunya pertumbuhan badan, menurunnya daya kerja, gangguan pada perkembangan mental dan kecerdasan serta berbagai jenis penyakit lainnya. Dalam pidatonya di pembukaan Konferensi Kerja Nasional Perubahan Menu Makanan pada 22 Juli 1974, Presiden Soeharto menyinggung persoalan gizi ini lewat ungkapan, “Dapat saja orang kenyang makan, tetapi masih lapar gizi.”
Baca juga: Program Makanan Bergizi Era Orde Baru
“Memang, masalah pembangunan suatu bangsa bukanlah hanya berkisar pada masalah pangan untuk mengisi perut. Akan tetapi juga sangat terang bahwa perut lapar orang tidak akan mungkin membangun; malahan seringkali bangsa yang lapar berobah menjadi kumpulan orang-orang pemarah. Karena itu masalah pangan sebagai kebutuhan pokok manusia harus mendapatkan perhatian yang besar dalam seluruh proses pembangunan tadi. Pangan bukan saja merupakan kebutuhan pokok, akan tetapi juga menjadi prasyarat untuk gerak pembangunan berikutnya agar kita dapat menjadi bangsa yang sehat jasmani dan rokhani, agar dapat menjadi bangsa yang cerdas fikirannya dan luhur budinya,” terang Presiden Soeharto dalam pidatonya seperti tersua dalam Inventaris Arsip Sekretariat Negara: Seri Pidato Presiden Soeharto 1966--1998 Jilid 2, No. 1349.
Diversifikasi Pangan
Berbagai program turunan kemudian digagas sebagai tindak lanjut Inpres Presiden No.14/1974 sekaligus agar sejalan dengan program nasional UPGK. Pada 19 Februari 1975, Komisi Teknik Perbaikan Menu Makanan Rakyat dibentuk di bawah deputi bidang Sosial-Budaya Bappenas. Komisi ini bertugas sebagai forum koordinasi tingkat menteri dalam merumuskan bersama perencanaan lintas-sektor mengenai pelaksanaan teknis usaha perbaikan menu makanan rakyat.
Pada 18 Januari 1978, diselenggarakan Rapat Kerja Nasional Perbaikan Menu Makanan Rakyat di kantor kepresidenan Bina Graha. Dalam lokakarya itu diungkapkan, permasalahan gizi yang banyak terjadi masih berkisar pada kekurangan dalam berbagai unsur gizi. Selain kalori dan protein, kekurangan juga meliputi yodium, zat besi, dan vitamin A. Kekurangan kalori dan protein dapat menghambat perkembangan jasmani dan kecerdasan anak pra-sekolah usia di bawah lima tahun. Anak-anak ini bahkan dapat mengalami kebutaan mata apabila kekurangan vitamin A. Sementara itu, kekurangan yodium dapat mengakibatkan penyakit gondok.
Presiden Soeharto saat itu menekankan program iodisasi garam bagi anak-anak dan ibu hamil. Selain itu, kekurangan zat gizi diharapkan dapat terpenuhi melalui penganekaragaman jenis makanan rakyat. Konsep ini kemudian dikenal dengan sebutan diversifikasi pangan dengan produk unggulan “Tekad”, yaitu: telo (ketela), kacang, dan jagung.
“Mengenai beras adalah satu-satunya bahan pangan terpenting itu menyesatkan! Ikan, sayur-sayuran, ubi-ubian, buah-buahan juga tidak kalah penting. Dan, semua ini bisa dihasilkan dengan cara-cara yang jauh lebih mudah dari menanam padi!” kata Presiden Soeharto.
Baca juga: Mengapa Indonesia Tergantung pada Beras?
Sebab kemudahan itu, Soeharto menganjurkan rumah-rumah di kota besar –betapapun sempitnya– masih mempunyai halaman atau pekarangan. Apabila setiap jengkal tanah dimanfaatkan untuk produksi pangan seperti protein daun, rempah-rempah, bahan-bahan obat tradisionil, sayur-mayur, buah-buahan, dan sebagainya. Mungkin juga untuk peternakan, perikanan, dan sebagainya. Di samping untuk meningkatkan mutu gizi makanan sehari-hari, kelebihannya dapat dijual. Ini jelas menguntungkan pemilik pekarangan dan memantapkan usaha-usaha dalam menanggulangi masalah pangan nasional.
“Masyarakat Sanghyang Damar tanam tanaman di pekarangannya,” demikian diberitakan Berita Yudha, 29 Mei 1984.
Apa yang dikemukakan Presiden Soeharto tentang tanaman pekarangan untuk pangan, sepertinya dieksekusi dengan baik oleh warga Sanghyang bertahun-tahun sesudahnya. Sanghyang Damar merupakan salah satu unit perkebunan PTP XI milik negara. Letaknya di daerah Banten Selatan. Untuk mewujudkan UPGK, ibu-ibu di sana menanami pekarangan mereka dengan tanaman apotik hidup seperti, bayam, ketela, tomat, cabe, pisang, dan katuk.
“Suana lingkungan perkebunan Sanghyang Damar yang begitu nyaman dengan pohon karet, semakin tambah nyaman dengan tanaman pekarangannya,” sebut Berita Yudha.
Gizi Masih Belum Teratasi
Dalam kenyataannya, program diversifikasi pangan maupun tanaman pekarangan tidak begitu signifikan dalam memompa peningkatan gizi masyarakat secara umum. Pun demikian dengan program penanganan gizi yang dibentuk mulai dari yang sifatnya pengawasan atau mitigasi seperti Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) hingga Pedoman Umum Gizi Seimbang.
“Didalam Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) yang baru saja selesai disusun, masalah keamanan makanan, juga diperhatikan secara khusus, terutama yang menyangkut penggunaan Bahan Tambahan Makanan (BTM) dan pentingnya memperhatikan label makanan (tanggal kadaluarsa dan komposisi gizi),” lansir Berita Yudha, 12 April 1995.
Baca juga: NGOBRAS Stunting dan Sejarahnya di Indonesia
Dari semua program itu, pada kenyataannya kondisi gizi di masyarakat Indonesia hanya meningkat relatif kecil. Dalam Berita Yudha, 4 Juli 1983, misalnya, diwartakan tentang kegiatan UPGK di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, telah menurunkan sebanyak dua persen jumlah anak usia di bawah lima tahun yang bergizi kurang baik. Sementara itu, anak-anak yang memiliki gizi baik mencapai 54,8 persen. Itu berarti sebanyak 45,2 persen anak-anak masih belum memperoleh asupan gizi yang cukup. Dari data populasi balita keseluruhan, 7,2 persen di antaranya berstatus gizi buruk.
Hampir 10 tahun kemudian, menurut Harian Bernas, 14 Oktober 1992, Kulonprogo (dan Gunungkidul) masih rawan gizi. Padahal, program UPKG telah bergulir sejak dasawarsa 1970-an. Itu masih di salah satu kabupaten di Jawa. Belum lagi daerah yang berada di kawasan timur Indonesia atau desa-desa tertinggal lainnya.
“Warga Gunungkidul dan Kulonprogo, hingga saat ini masih rawan gizi. Berkaitan dengan hal itu dua kabupaten tersebut dipilih untuk program khusus diversifikasi pangan dan gizi,” demikian diwartakan Bernas.
Belakangan, di pengujung Orde Baru, pemerintah memberlakukan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi anak-anak sekolah tingkat SD. Namun, program pamungkas ini pun tidak menjawab persoalan gizi di Indonesia. Tak lama sesudah PMT-AS bergulir, terjadi krisis moneter dan krisis politik yang menyebabkan Soeharto turun setelah tiga dekade berkuasa. Dengan demikian, program-program penanganan gizi produk Orde Baru belum berhasil sepenuhnya. Masalah gizi buruk tetap berlanjut bahkan ketika Orde Baru telah lama tumbang.
Menurut Widjojo Nitisastro, Menteri Koordinator Ekonomi 1973—1983, pelaksanaan program gizi skala nasional yang diusung pemerintah Orde Baru tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pada tingkat pemerintah pusat, kerjasama lintas sektoral kurang selaras dalam merumuskan pengertian yang sama atas apa yang menjadi tujuan program tersebut. Kendala juga terjadi pada sinkronisasi serta koordinasi pada tingkat daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, ataupun kecamatan dan juga desa. Begitupun juga dengan keserasian antara apa yang ditetapkan atau diputuskan pada tingkat pusat serta pelaksanaan pengertian tersebut pada tingkat daerah.
Baca juga: Perancang Ekonomi Orde Baru
“Ini tidak senantiasa terjadi sebagaimana yang diharapkan, sebab kita semua maklum bahwa suatu pengertian mungkin interpretasinya berbeda, persepsinya berbeda, dan ini bisa menimbulkan kericuhan dalam pelaksanaan pada tingkat daerah,” terang Widjojo dalam Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro.
Selain itu, lanjut Widjojo, program tidak berjalan optimal gara-gara manajemen organisasi penyelenggara negara yang kurang efektif. Salah satunya gara-gara kebanyakan rapat. Widjodjo kadang-kadang heran melihat pejabat yang kerjanya rapat terus. Rapat dari komunikasi ini ke komunikasi itu dan seterusnya. Kalau tidak rapat tidak ada keputusan. Kapan waktu untuk membaca dan menulis bahan yang baik, mengerjakan pekerjaan penyuluhan dan sebagainya, kalau terus menerus rapat.
“Rapat di berbagai tingkatan perlu, rapat itu penting, tetapi pemikiran untuk pelaksanaan dan hal-hal yang bisa dilakukan tanpa rapat bisa kita lakukan. Ini suatu segi. Kemudian di dalam segi rapat dan organisasi itu menyangkut biaya yang tidak kecil. Sehingga ada juga gejala biaya banyak yang diperlukan untuk keperluan organisasi, rapat, biaya perjalanan, dan sebagainya,” ujar Widjodjo.
Berkaca dari sejarahnya, persoalan gizi rupanya jauh lebih kompleks dari sekadar urusan makanan. Ia menyangkut hajat hidup tiap-tiap warga negara. Untuk itu, penanganan gizi mesti berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan, perluasan lapangan kerja dan akses pendidikan untuk semua, hingga penyelenggaraan negara yang cakap serta bersih. Niscaya persoalan gizi dapat teratasi dengan sendirinya.








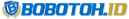
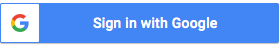

Tambahkan komentar
Belum ada komentar